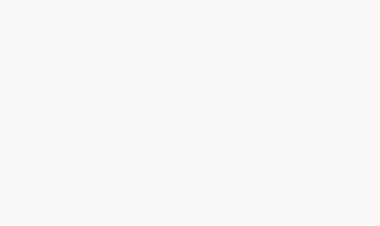Menata rantai distribusi elpiji yang lebih adil
Rantai distribusi barang subsidi elpiji 3 kilogram (kg) yang kini hanya sampai pangkalan, menimbulkan berbagai reaksi ...

Jakarta (ANTARA) - Rantai distribusi barang subsidi elpiji 3 kilogram (kg) yang kini hanya sampai pangkalan, menimbulkan berbagai reaksi dan konsekuensi bagi masyarakat.
Tercatat mulai 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang melarang penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer.
Kini, distribusi elpiji 3 kg hanya diperbolehkan melalui pangkalan resmi yang terdaftar. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sudah mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
Kebijakan ini harus diakui menjadi pukulan tersendiri terutama bagi konsumen yang selama ini mengandalkan kemudahan mendapatkan gas melon (elpiji 3 kg) di tingkat pengecer.
Pertanyaannya, apakah sistem ini benar-benar menjadi solusi bagi subsidi tepat sasaran, atau justru memperumit akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok ini, terutama menjelang Ramadhan yang identik dengan lonjakan konsumsi?
Dari sisi pemahaman tentang pemerataan kesejahteraan dan penyaluran subsidi, dapat dilihat ada dua aspek utama yang harus ditelaah dalam kebijakan ini, yaitu efektivitas distribusi subsidi dan dampaknya terhadap masyarakat kecil.
Dalam teori kebijakan energi, pengurangan rantai distribusi memang bertujuan menghindari kebocoran dan memastikan subsidi hanya dinikmati oleh kelompok yang berhak. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini justru dapat menciptakan kesenjangan akses.
Bagi masyarakat perkotaan, mungkin kebijakan ini hanya berdampak pada sedikit perubahan pola pembelian, dari pengecer ke pangkalan.
Namun, bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pangkalan resmi, ini adalah tantangan besar. Banyak rumah tangga, pedagang kaki lima, dan pelaku UMKM yang mengandalkan elpiji 3 kg untuk kebutuhan harian mereka.
Sebelum kebijakan ini diberlakukan, mereka bisa mendapatkannya dengan mudah di warung-warung kecil sekitar rumah.
Kini, mereka harus mengeluarkan ongkos tambahan untuk pergi ke pangkalan resmi yang mungkin letaknya jauh. Biaya transportasi ini, jika dikalkulasikan dalam skala bulanan, dapat menjadi beban ekonomi yang tidak kecil.
Baca juga:
Baca juga:
Baca juga:
Praktik Percaloan
Menjelang Ramadhan, kebijakan ini menjadi semakin krusial karena permintaan elpiji biasanya meningkat.
Tanpa distribusi yang fleksibel, kemungkinan besar akan terjadi antrean panjang di pangkalan atau bahkan kelangkaan di beberapa wilayah.
Situasi ini dapat mendorong munculnya praktik percaloan baru di tingkat pangkalan, di mana mereka yang memiliki akses lebih mudah ke stok elpiji akan mencari keuntungan dari kesulitan masyarakat lain.
Ini tentu bertentangan dengan tujuan awal kebijakan, yaitu memastikan subsidi tepat sasaran dan menghindari eksploitasi harga di pasar gelap.
Ada anggapan bahwa sistem baru ini secara tidak langsung akan memaksa masyarakat untuk beralih ke elpiji nonsubsidi, seperti tabung 12 kg.
Secara ekonomi, argumen ini masuk akal. Jika masyarakat menghadapi kesulitan mengakses elpiji 3 kg, mereka akan mencari alternatif yang lebih mudah didapat.
Namun, apakah masyarakat kecil yang selama ini menggunakan elpiji 3 kg benar-benar mampu beralih ke elpiji 12 kg yang harganya jauh lebih mahal?
Bagi sebagian keluarga dan pelaku usaha mikro, kenaikan biaya ini bisa menggerus pendapatan mereka yang sudah terbatas.
Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sistem distribusi berbasis digital yang lebih terintegrasi.
Baca juga:
Kemudahan Akses
Sejauh ini, sistem digitalisasi pembelian elpiji 3 kg menggunakan pencatatan KTP masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya diterapkan secara seragam di semua daerah.
Pemerintah perlu mempercepat sistem ini agar pembelian elpiji subsidi lebih terkontrol tanpa harus memangkas rantai distribusi yang selama ini membantu masyarakat dalam hal kemudahan akses.
Digitalisasi ini dapat dipadukan dengan program subsidi langsung berbasis rekening, seperti yang telah diterapkan dalam bantuan sosial lainnya.
Jika kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi, maka pendekatan yang lebih tepat adalah melalui edukasi dan insentif bertahap untuk mendorong migrasi ke energi alternatif.
Di beberapa negara, skema subsidi berbasis konsumsi energi telah diterapkan, di mana rumah tangga yang menggunakan energi dalam jumlah wajar tetap mendapatkan dukungan, sementara mereka yang konsumsi energinya lebih tinggi harus membayar lebih.
Pendekatan ini lebih adil dibandingkan sekadar mempersulit akses ke barang subsidi tanpa solusi yang jelas.
Keberlanjutan subsidi energi memang menjadi isu yang kompleks. Pemerintah harus mencari keseimbangan antara menjaga keuangan negara dan melindungi kelompok rentan dari dampak kebijakan yang tidak proporsional.
Tanpa mekanisme transisi yang memadai, kebijakan ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru, di mana mereka yang lebih kuat secara ekonomi akan dengan mudah beradaptasi, sementara kelompok masyarakat bawah harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dari perspektif kebijakan energi, yang dibutuhkan bukan hanya pemangkasan rantai distribusi, tetapi juga mekanisme pemantauan yang lebih ketat.
Jika tujuan akhirnya adalah subsidi yang lebih tepat sasaran, maka pendekatannya harus berbasis data yang akurat dan sistem yang tidak membebani masyarakat dalam mengakses hak mereka.
Tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menciptakan ketimpangan baru yang dapat menimbulkan efek domino bagi sektor ekonomi yang lebih luas.
Baca juga:
Baca juga:
Baca juga:
*) Penulis adalah aktivis sosial ekonomi kemasyarakatan dan kepemudaan; serta Ketua Umum DPP Generasi Muda Mathla'ul Anwar.
Copyright © ANTARA 2025