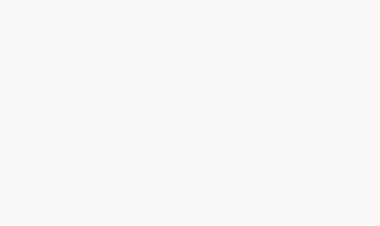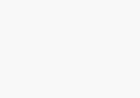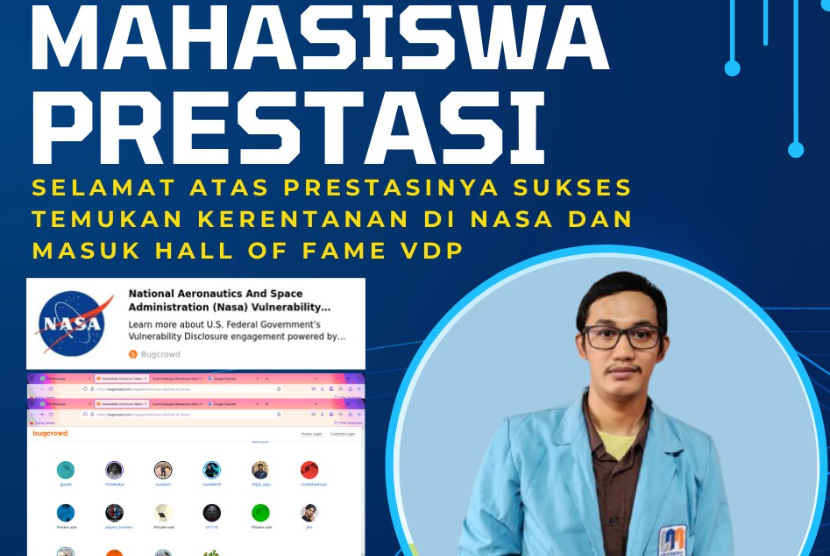Dosa peradaban terhadap lingkungan di era teknologi dan akal imitasi
"Air tenang menghanyutkan." Peradaban yang tampak megah di atas fondasi ilmu dan teknologi modern ternyata ...

Jakarta (ANTARA) - "Air tenang menghanyutkan." Peradaban yang tampak megah di atas fondasi ilmu dan teknologi modern ternyata menyembunyikan arus deras kehancuran ekologi. Krisis lingkungan bukan sekadar dampak dari keserakahan manusia, melainkan juga lahir dari cara kita berpikir tentang alam: apakah ia sekadar sumber daya, ataukah ibu yang harus dijaga?
Kini, di era kecerdasan buatan (AI — Akal Imitasi), nanoteknologi, dan rekayasa biologis seperti stem cells serta nanoimunobioteknomedisin, paradigma eksploitasi semakin kompleks, merambah hingga ke batas moral dan etika.
Martin Heidegger memperingatkan dalam The Question Concerning Technology bahwa teknologi bukan sekadar alat, tetapi cara manusia menyingkap realitas. Alam kini tak lagi "diizinkan" menunjukkan dirinya, melainkan dipaksa tunduk dalam logika kapitalisme data dan eksploitasi bioindustri.
Filsuf asal Prancis Jacques Derrida, dengan dekonstruksinya, menantang oposisi biner antara manusia dan alam — mempertanyakan klaim superioritas manusia atas lingkungan sebagai suatu konstruk yang bisa diretas dan direstrukturasi.
Awal Mula Dosa Kita
Sejak era pencerahan (enlightenment), manusia mulai memandang alam sebagai mesin raksasa yang dapat diukur, dianalisis, dan dimanipulasi. Carolyn Merchant dalam The Death of Nature menggambarkan bagaimana revolusi ilmiah abad ke-16 mengubah metafor alam dari terra mater (ibu bumi) menjadi objek mekanistik yang boleh dieksploitasi. Alam bukan lagi sesuatu yang sakral, tetapi sumber daya yang harus ditundukkan.
William Rees, penggagas ecological footprint, menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tak terkendali memicu ekosida, pemusnahan sumber daya dan ekosistem yang diperlukan dalam kehidupan manusia dengan cara eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam secara masif.
Hutan tropis ditebang tanpa henti, lautan menjadi asam, biodiversitas menyusut drastis, dan perubahan iklim mempercepat kehancuran ekosistem. Kita telah memasuki era Antroposen — zaman geologi di mana jejak tangan manusia lebih mendominasi lanskap bumi ketimbang proses alami.
Namun, dengan hadirnya AI, realitas semakin dimediasi oleh algoritma yang memproses lingkungan bukan sebagai entitas bernyawa, tetapi sebagai big data yang dapat dieksploitasi.
Munculnya Etika Lingkungan
Aldo Leopold dalam A Sand County Almanac mengajukan gagasan Land Ethics: moralitas harus diperluas tidak hanya dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup lain. Landasan berpikir ini menggeser paradigma dari antroposentrisme -yang menempatkan manusia sebagai pusat segala hal di alam semesta- menuju ekosentrisme yang menganggap keseluruhan ekosistem sebagai entitas yang memiliki intrinsik.
Gagasan etika lingkungan berkembang ke berbagai arah. Pertama, antroposentrisme moderat. Alam harus dijaga demi kesejahteraan manusia. Prinsip keberlanjutan menjadi pijakan utama.
Kedua, zoosentrisme dan biosentrisme. Zoosentrisme menekankan perjuangan hak-hak binatang sementara biosentrisme mengenali hak alam semesta dan berusaha menjaga keberagaman ekosistem dengan tidak mengeksploitasi satu spesies di atas yang lainnya.
Ketiga, ekosentrisme yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem tanpa memihak pada satu entitas tertentu.
Keempat, deep ecology, etika yang memandang bahwa manusia merupakan bagian integral dari lingkungannya. Arne Naess mengajukan delapan prinsip ekologi mendalam, termasuk pengurangan populasi manusia dan kesadaran bahwa nilai kehidupan non-manusia tidak bergantung pada manusia.
Kelima, ecofeminisme: Rosemary Radford dan Francoise d’Eaubonne mengkritisi bagaimana patriarki tidak hanya menindas perempuan tetapi juga memperlakukan alam dengan cara yang sama: sebagai objek eksploitasi.
Dosa Ekologi dan Solusi
Manusia telah membayar mahal untuk dosa ekologinya. Bencana alam, krisis iklim, dan punahnya spesies bukan sekadar peristiwa acak, tetapi konsekuensi dari cara kita memperlakukan lingkungan.
Jika kita tidak ingin sejarah mencatat kita sebagai peradaban yang membunuh ibunya sendiri, ada beberapa langkah yang harus diambil.
Pertama, untuk akademisi. Perlu pendekatan multidisipliner dalam riset lingkungan, menggabungkan filsafat, sains, dan humaniora untuk menciptakan perspektif baru dalam etika lingkungan yang mempertimbangkan AI dan bioetika.
Kedua, untuk masyarakat. Kesadaran bahwa setiap tindakan konsumsi memiliki dampak ekologis. Mulailah dari perubahan kecil: kurangi plastik, hentikan fast fashion, dan dukung produk berkelanjutan.
Ketiga, untuk pemerintah. Regulasi yang lebih ketat dalam perlindungan lingkungan, penghentian eksploitasi sumber daya secara masif, dan penerapan kebijakan ekonomi hijau.
Keempat, untuk pembuat kebijakan. Reformasi paradigma pembangunan: tidak lagi berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas, tetapi pada keseimbangan ekologi dan keadilan sosial.
Paus Fransiskus dalam ensiklik (surat amanat Paus) “Laudato Si” yang dikeluarkan pada 2015 mengajak kita semua untuk menjaga alam dari kehancuran. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, namun meminjamnya dari anak cucu kita.
Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apakah mereka akan hidup dalam dunia yang masih hijau atau hanya mewarisi reruntuhan peradaban. Kemajuan peradaban yang seharusnya membawa kesejahteraan tidak seharusnya menjadi senjata yang merusak keseimbangan alam. Ketika teknologi dan akal buatan menggantikan kebijaksanaan alami, manusia semakin jauh dari harmoni dengan lingkungan.
Kita harus segera menyadari itu, agar tidak meninggalkan warisan kehancuran bagi generasi mendatang.
*) Dokter Dito Anurogo MSc PhD adalah pembelajar filsafat, alumnus IPCTRM College of Medicine Taipei Medical University Taiwan, dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia, peneliti Institut Molekul Indonesia
Copyright © ANTARA 2025