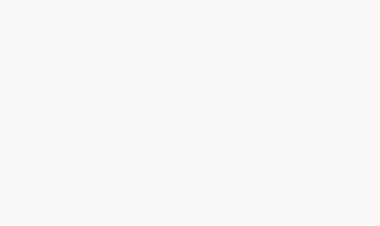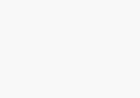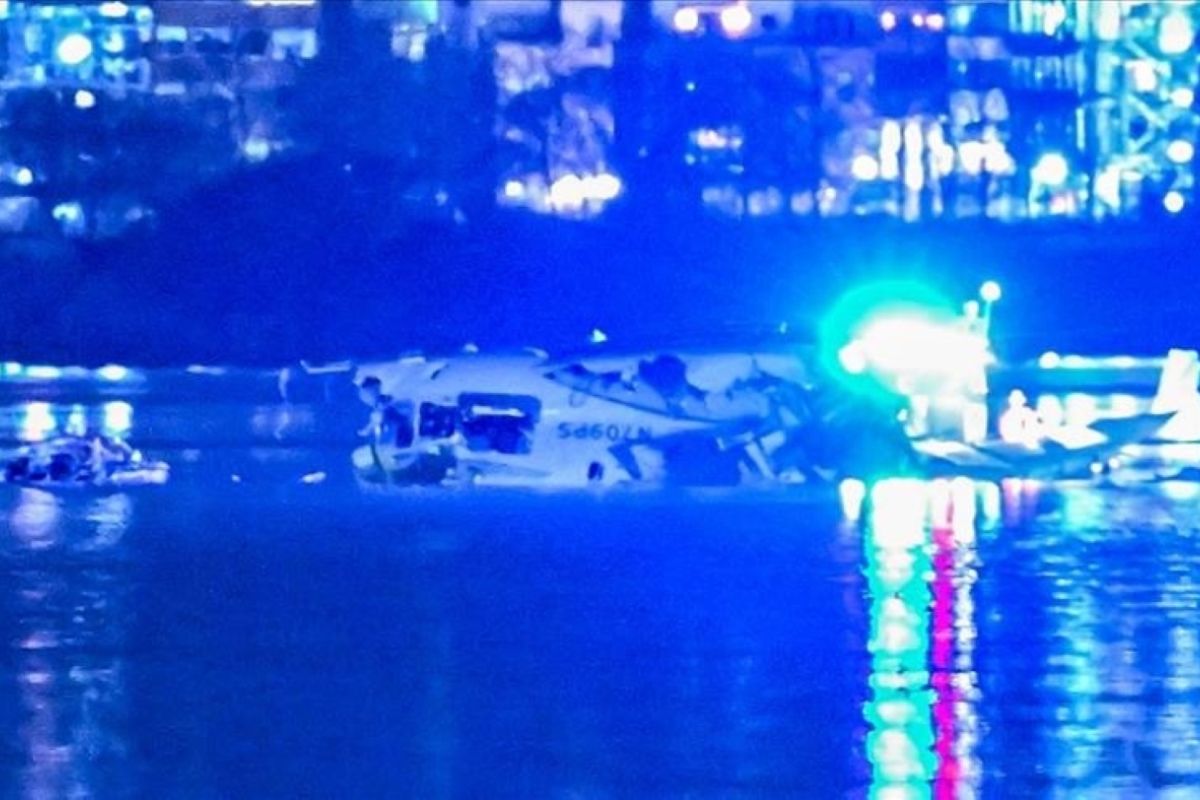Mari berandai-andai jika tiba-tiba 1 dolar AS setara Rp8.170
Kegegeran di tengah warganet sempat terjadi pada akhir pekan lalu ketika hasil penelusuran di Google menemukan bahwa ...

Jakarta (ANTARA) - Kegegeran di tengah warganet sempat terjadi pada akhir pekan lalu ketika hasil penelusuran di Google menemukan bahwa tingkat nilai tukar mata uang 1 dolar adalah setara Rp8.170,65.
Sontak, hal itu membuat Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyatakan bahwa level nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagaimana yang ada di Google ketika itu bukan merupakan level yang seharusnya. Data BI mencatat kurs Rp16.312 per dolar AS pada tanggal 31 Januari 2025.
Sementara itu, Google mengatakan kesalahan informasi nilai tukar tersebut berasal dari data konversi pihak ketiga. Pihak penyedia data pun segera diminta untuk memperbaiki kekeliruan itu.
Memang membuat penasaran untuk membayangkan apa yang terjadi bila mata uang rupiah menguat tiba-tiba terhadap dolar AS. Dalam kajian ilmu ekonomi itu sendiri, fenomena naiknya nilai mata uang terhadap nilai mata uang asing dalam sistem nilai tukar itu biasa disebut sebagai "apresiasi", sedangkan bila terjadi sebaliknya atau penurunan nilai mata uang adalah "depresiasi".
Apresiasi mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya secara tiba-tiba dan cepat dapat menimbulkan banyak dampak. Mata uang yang lebih kuat membuat barang dan jasa dari negara tersebut menjadi lebih mahal untuk diekspor oleh pembeli asing, sehingga bisa menyebabkan penurunan daya saing ekspor, dan mungkin merugikan industri yang bergantung pada ekspor.
Di sisi lain, impor menjadi lebih murah, yang dapat menguntungkan konsumen dan dunia usaha yang bergantung pada barang-barang dari luar negeri. Hal ini dapat menurunkan inflasi, tetapi juga dapat merugikan produsen dalam negeri yang menghadapi persaingan dengan barang-barang luar negeri yang lebih murah.
Selain itu, jika suatu negara mempunyai utang luar negeri, terutama dalam mata uang dolar, maka akan lebih mudah untuk melunasi utang tersebut. Kurs yang lebih kuat berarti dibutuhkan lebih sedikit mata uang lokal untuk dikonversi menjadi dolar untuk pembayaran utang.
Sementara nilai mata uang yang terapresiasi dengan cepat dalam teori juga dapat menjadikan negara ini tempat yang menarik bagi investasi asing, karena investor mungkin melihatnya sebagai tanda kekuatan ekonomi. Namun, hal ini juga dapat menghalangi investasi di industri berbasis ekspor, karena industri tersebut mungkin akan kesulitan menghadapi penguatan mata uang.
Sebaliknya, apresiasi mata uang yang cepat berpotensi dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, karena sektor-sektor yang berorientasi ekspor bisa terkena dampaknya, sehingga menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, sementara industri-industri yang mendapatkan keuntungan dari impor yang lebih murah akan mengalami pertumbuhan.
Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidaksukaan, terutama di kalangan pekerja di sektor yang terkena dampak. Singkatnya, apresiasi mata uang yang cepat dapat menciptakan peluang sekaligus tantangan, sehingga diperlukan tindakan penyeimbang yang tepat bagi pemerintah untuk mengelola perubahan ekonomi sambil menjaga stabilitas politik.
Baca juga:
Baca juga:
Yen Jepang
Berbagai penjelasan yang telah disebut di atas dapat disebut sebagai penjelasan teoritis. Namun, bagaimana dengan catatan sejarah, adakah contoh nyata dari berbagai mata uang yang tiba-tiba menguat signifikan hanya dalam jangka waktu beberapa tahun?
Satu contoh yang terkemuka terkait hal itu adalah penguatan mata uang yen Jepang pada periode 1985-1987, setelah terjadinya kesepakatan yang disebut sebagai Plaza Accord.
Plaza Accord itu sendiri adalah perjanjian antara negara-negara ekonomi besar (AS, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris) di Hotel Plaza di Kota New York, AS, pada 22 September 1985, untuk mendepresiasi dolar AS dan memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan global. AS setuju untuk menurunkan nilai mata uangnya setelah defisit perdagangannya terus naik.
Hasil dari Plaza Accord adalah kelima negara itu setuju melakukan intervensi di pasar mata uang untuk mendepresiasi dolar. Bank sentral negara-negara tersebut sepakat untuk menjual dolar AS dan ditukar dengan mata uang lain, terutama yen, demi menekan nilai dolar.
Dengan membanjiri pasar dengan dolar AS, serta dikombinasikan dengan meningkatnya permintaan terhadap mata uang yen Jepang dan mark Jerman, membantu menurunkan nilai dolar. Yen Jepang pun terapresiasi dengan cepat terhadap dolar AS.
Setelah Plaza Accord pada 1985, yen Jepang terapresiasi hampir 50 persen terhadap dolar AS hanya dalam dua tahun. Yen Jepang menguat dari sekitar 240 yen/dolar pada 1985 menjadi sekitar 120 yen/dolar pada 1987.
Penguatan yen setelah Plaza Accord mencerminkan kekuatan ekonomi Jepang yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta semakin menonjolnya daya saing negara Matahari Terbit itu dalam perdagangan global. Seiring apresiasi yen, produk Jepang menjadi lebih mahal di pasar luar negeri, tetapi Jepang juga lebih mampu bersaing secara global.
Baca juga:
Gelembung spekulatif
Apresiasi yen yang cepat ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian Jepang, termasuk melemahkan daya saing ekspornya dan berkontribusi terhadap gelembung spekulatif terutama di sektor real estat dan saham di Jepang pada akhir tahun 1980-an.
Untuk melawan dampak negatif penguatan yen terhadap ekspor, bank sentral Jepang (BOJ) menurunkan suku bunga secara signifikan pada akhir tahun 1980-an. Idenya adalah untuk merangsang permintaan domestik dan mendukung perekonomian karena dengan menjadikan pinjaman lebih murah, diharapkan akan mendorong investasi.
Kebijakan suku bunga rendah ini berlangsung selama beberapa tahun, menyebabkan ledakan kredit dan peningkatan pesat harga pasar saham dan real estat. Investor dan banyak orang memanfaatkan kredit murah dengan mulai menggelontorkan dana ke real estat dan saham.
Kombinasi investasi spekulatif dalam real estat dan saham menciptakan gelembung ekonomi, suatu periode di mana harga aset sangat tinggi, lebih didorong oleh spekulasi dan kemudahan mendapatkan uang dibandingkan nilai riil dari aset itu sendiri.
Pada tahun 1990, BOJ mulai menyadari bahaya gelembung spekulatif dan berusaha menenangkan perekonomian dengan menaikkan suku bunga. Langkah ini bertujuan mengurangi kelebihan likuiditas yang mendorong kenaikan harga aset.
Pengetatan kredit dan kenaikan suku bunga memicu jatuhnya pasar saham dan harga real estat. Pada awal 1990-an, Jepang memasuki periode stagnasi ekonomi, dan gelembung ekonomi tersebut pecah yang mengakibatkan rendahnya pertumbuhan dalam jangka waktu yang lama, jatuhnya harga aset, dan krisis perbankan.
Pecahnya gelembung ini menandai awal dari fenomena yang disebut "Dekade Hilang" Jepang (yang berlangsung hingga tahun 2000-an), di mana negara tersebut berjuang melawan deflasi, pertumbuhan yang stagnan, tingginya angka pengangguran, dan banyaknya kredit macet akibat runtuhnya gelembung tersebut.
Tidak hanya yen Jepang, ada contoh historis lainnya dari sejumlah mata uang lain yang mengalami tingkat apresiasi yang secara cepat selama jangka waktu beberapa tahun, tetapi dampaknya malah menimbulkan efek yang negatif pada jangka panjang terhadap sejumlah indikator sosioperekonomian dari negara itu.
Baca juga:
Baca juga:
Krona Islandia
Krona, mata uang Islandia, mengalami apresiasi yang kuat antara tahun 2001 dan 2008, meningkat lebih dari 40 persen terhadap euro selama periode ini. Penguatan krona ini didorong kombinasi beberapa faktor, termasuk tingginya suku bunga di Islandia yang menarik modal asing, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat yang dipicu oleh pertumbuhan yang kuat di sektor-sektor seperti pariwisata, perikanan, dan perbankan.
Namun, Islandia pada 2008 mengalami krisis setelah krisis finansial global yang bermula di AS menyebar ke Eropa, ditambah tiga bank terbesar di Islandia gagal memenuhi kewajibannya sehingga membuat sektor perbankan ambruk akibat terjadinya investasi berisiko dan sangat sembrono.
Bank-bank tersebut banyak terlibat di pasar internasional, meminjam uang dari investor asing dan berkembang pesat, seringkali melalui instrumen keuangan yang rumit dan bersifat sangat kompleks. Faktor pinjaman luar negeri yang berlebihan, didorong kurangnya regulasi dan pengawasan keuangan yang memadai, merupakan pemicu keruntuhan dari krisis keuangan di Islandia ketika itu.
Meski bukan menjadi penyebab utama, terapresiasinya krona dengan cepat dapat disebut sebagai salah satu faktor pemicu. Hal itu karena menjelang krisis, krona dipandang sebagai mata uang dengan imbal hasil tinggi, sehingga menarik investor asing yang mencari imbal hasil lebih baik dalam perekonomian Islandia yang berkembang pesat.
Ketika krona terapresiasi, hutang ini menjadi lebih murah dalam bentuk mata uang Islandia itu, sehingga mendorong terjadinya peminjaman. Namun, ketika mata uang krona mulai terdepresiasi secara tajam setelah krisis tersebut (yang merupakan konsekuensi alami dari runtuhnya sektor perbankan dan hilangnya kepercayaan investor), utang dalam mata uang asing ini melonjakkan biayanya, memberikan tekanan yang sangat besar pada peminjam dan sistem keuangan Islandia.
Berbagai peristiwa dalam lintasan sejarah perekonomian global itu membuat Indonesia dapat mengambil pelajaran. Salah satunya adalah, secara umum terjadinya apresiasi mata uang yang cepat dapat menjadi pedang bermata dua.
Meskipun hal ini dapat memberikan beberapa manfaat jangka pendek seperti mengurangi biaya impor dan menandakan kekuatan ekonomi, risiko dan tantangannya sering kali lebih besar daripada dampak positifnya, terutama jika perekonomian terlalu bergantung pada ekspor atau banyaknya spekulasi di sektor keuangan.
Apresiasi mata uang yang cepat (seperti tiba-tiba 1 dolar setara Rp8170) memang dapat memberikan beberapa manfaat, tetapi sering kali mengandung peringatan dan risiko signifikan yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati.
Untuk itu, lebih baik bila dilakukan pendekatan perubahan mata uang yang lebih bertahap, serta didukung oleh kebijakan ekonomi yang kuat dan reformasi struktural, sehingga lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.
Baca juga:
Baca juga:
Copyright © ANTARA 2025