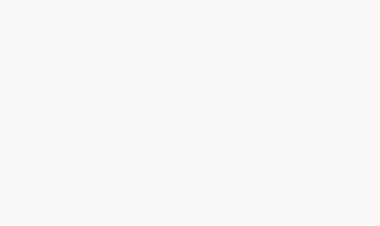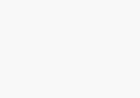Melawan PSN dengan Menenun: Kisah Perempuan Adat Helong NTT Menolak Punah
Di era Jokowi, Bendungan Kolhua sempat menyandang status sebagai PSN dan merupakan satu dari tujuh bendungan yang rencananya dibangun di NTT.

TEMPO.CO, Jakarta - Keseharian warga Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (, banyak diisi dengan pergi ke sawah. Datangnya musim hujan membuat warga memanfaatkannya untuk menyemai lahan dengan padi, jagung, dan tanaman sayur. Di area perbukitan yang dialiri oleh sungai ini, warga Kolhua mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Di samping itu, Kolhua juga merupakan rumah bagi 1300 jiwa Suku Helong, suku pertama yang mendiami Kota Kupang.
Sekilas, kehidupan Suku Helong di Kolhua tampak baik-baik saja. Warga masih beraktivitas dan bekerja seperti biasanya. Namun selama dua dekade terakhir, Suku Helong harus berjuang melawan pembangunan Bendungan Kolhua yang mengancam eksistensi mereka. Salah satu warga Suku Helong, Atalya Taklale, menceritakan perjuangan mereka mempertahankan lahan pada hampir 11 tahun lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan,

Ketika itu, waktu menunjukkan pukul empat pagi ketika Atalya Taklale bersama mama-mama lainnya di Kolhua mulai bekerja di dapur. Hari itu pada April 2014, Suku Helong berencana menggelar demonstrasi seharian penuh di depan Kantor Gubernur NTT dan Kantor DPRD Kota Kupang untuk menolak pembangunan bendungan. Di dapur, Atalya dan para mama mempersiapkan ketupat, ubi, dan pisang rebus sebagai bekal bagi peserta aksi. Usai memasak, Atalya pun bersiap-siap untuk ikut demonstrasi. “Ketika ada penolakan, pasti kami tidak akan duduk diam,” ucap Atalya kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Kamis, 30 Januari 2025.
Demonstrasi pada April 2014 merupakan satu dari aksi berjilid-jilid oleh Suku Helong. Satu tahun sebelumnya, misalnya, mereka mengadakan ritual adat di depan Kantor Wali Kota Kupang dengan menyembelih ayam jantan berwarna merah yang menjadi simbol perlawanan.
Gerakan perlawanan Suku Helong terhadap pembangunan Bendungan Kolhua sudah bermula sejak 1993. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Bendungan Kolhua sempat menyandang status sebagai Proyek Strategis Nasional () dan merupakan satu dari tujuh bendungan yang rencananya akan dibangun di Nusa Tenggara Timur. Tujuh bendungan ini diklaim akan mengatasi krisis air. Sampai saat ini, hanya Bendungan Kolhua yang belum dibangun.
 Potret
lahan pertanian milik Rally Bistolen, warga Kelurahan Kolhua,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lahan
ini masuk dalam lokasi yang diproyeksikan untuk pembangunan
Bendungan Kolhua. Foto diambil pada 2023. Dokumentasi Rally
Bistolen
Potret
lahan pertanian milik Rally Bistolen, warga Kelurahan Kolhua,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lahan
ini masuk dalam lokasi yang diproyeksikan untuk pembangunan
Bendungan Kolhua. Foto diambil pada 2023. Dokumentasi Rally
Bistolen
Rencana pembangunan bendungan membuat Atalya dan warga lainnya tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya, apabila bendungan dengan luas sekitar 116 hektare itu dibangun, maka akan menggusur 300 rumah, empat tempat ibadah, lahan pertanian, dan ekosistem alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi Suku Helong, khususnya perempuan.
Bagi Atalya yang merupakan ibu tunggal dengan tiga anak, alam adalah sumber kekuatan dan penghidupan. “Saya membesarkan anak-anak saya dalam pelukan alam,” ujar perempuan berusia 42 tahun itu. Selain mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian, Atalya juga menghasilkan kain tenun. Tenun, menurut Atalya, tidak dapat dipisahkan dari alam. Proses pewarnaan tenun Helong membutuhkan ramuan yang dibuat dari tanaman lokal seperti mengkudu dan tarum. Setelah dicelupkan ke dalam ramuan, benang dicelupkan ke dalam lumpur untuk merekatkan warnanya. Menurut Atalya, lumpur ini berbeda dari lumpur pada umumnya dan hanya bisa ditemukan di Kolhua.
Kedekatan antara alam dan tenun juga ditemukan lewat motif yang terinspirasi dari jambu hutan atau yang disebut sebagai kuhan bunga oleh warga setempat. Motif kuhan nyaris terlupakan dari budaya Helong, sampai akhirnya dihidupkan kembali oleh Mama Atalya usai dia menggalinya dari ingatan tua-tua. “Di mana ada kuhan, pasti di situ ada mata air. Ini menunjukkan bahwa sumber kehidupan dan kekayaan orang Kolhua dilihat dari pohon itu,” ucap dia.
Atalya mengatakan tenun yang dibuat denganproses alami memakan waktu selama satu setengah bulan dan dijual dengan harga Rp 3 juta. Dalam satu tahun, dia bisa menghasilkan dua-tiga tenun alami. Menjual tenun membuat Atalya memiliki alternatif penghasilan, terlebih ketika perubahan iklim menyebabkan gagal panen. Menurut Atalya, dampak El Nino yang terjadi pada 2024 masih bisa dia rasakan hingga hari ini. Bagi Atalya, menenun bisa dilakukan tanpa mengenal musim.
Di samping itu, menenun juga merupakan cara Atalya untuk menolak kepunahan Suku Helong. Saat ini, jumlah perempuan Helong yang menenun kian berkurang. Atalya bercerita, perempuan Helong yang menenun sebagian besar sudah berusia 60 tahun ke atas, sedangkan perempuan yang seusia dengannya sudah tidak aktif menenun. “Saya berharap ke depannya ada perempuan-perempuan Helong penerus, perempuan Helong yang hebat, yang terus menjaga dan melestarikan budaya Helong,” ujarnya.
Berbekal keinginan untuk mempertahankan identitas Helong, Atalya berinisiatif membuka kelas tenun bagi para generasi muda. Untuk mewujudkannya, Atalya dibantu oleh komunitas Solidaritas Perempuan Flobamoratas. Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Linda Tagie bercerita konsep kelas tenun yang ia kelola seperti sekolah alam. Di komunitas ini, anak-anak juga mendapat pelajaran mengidentifikasi tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai pewarna.
Linda mengatakan, perempuan adat seperti Atalya perlu diberi ruang seluas-luasnya dalam pembuatan kebijakan. Sebab, perempuan adat memiliki pengetahuan lokal yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan. “Dalam kondisi pemerintah jalan sendiri, di mana kebijakannya tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat atau perempuan akar rumput, mereka (perempuan adat) memilih bertahan dengan cara-cara kearifan lokal,” ujar dia.
Linda juga menyoroti keterkaitan antara pengetahuan lokal perempuan adat dan tradisiperlawanan nirkekerasan yang identik dengan kerja perawatan. Dia mencontohkan ketika Atalya dan mama-mama lainnya memasak ketupat untukpeserta aksi. “Kemampuan perempuan untuk menganyam (ketupat) itu kemudian juga dipakai sebagai alat perlawanan, karena seandainya perempuan tidak bisa menganyam, secara otomatis mereka juga akan kelaparan,” kata dia. Linda pun menegaskan kerja-kerja perawatan seperti yang dilakukan Atalya menjadi penyokong bagi advokasi Suku Helong dalam mempertahankan ruang hidup mereka.
Pendiri Komunitas Penjaga Budaya Helong, Rally Marthin Bistolen, mengatakan Suku Helong sudah ada di Kupang sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia. Namun sampai saat ini, pemerintah Kota Kupang dan Provinsi NTT belum mengakui Suku Helong di Kolhua sebagai masyarakat adat. Hal ini jugalah yang mendorong Rally dan beberapa tokoh masyarakat untuk mendirikan KPBH. Sampai saat ini, kata Rally, pemerintah tak pernah melakukan upaya apa pun untuk membantu memberdayakan Suku Helong. Dia mengatakan semua upaya untuk melestarikan budaya, termasuk dengan mengadakan Festival Budaya Helong, dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
 Rally
Bistolen, pendiri Komunitas Penjaga Budaya Helong, saat
bertani di sawahnya di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Foto diambil pada 2023.
Dokumentasi Rally Bistolen
Rally
Bistolen, pendiri Komunitas Penjaga Budaya Helong, saat
bertani di sawahnya di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Foto diambil pada 2023.
Dokumentasi Rally Bistolen
Alasan kedua, komunitas ini sekaligus menjadi wadah perjuangan untuk melawan pembangunan Bendungan Kolhua. Perjuangan Suku Helong pernah diwarnai konflik. Rally bercerita pada 2009, Wali Kota Kupang melaporkan tujuh warga ke kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik. Namun konflik itu terselesaikan usai dimediasi oleh eks Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay yang merupakan sesepuh Helong. “Kenapa kami harus berjuang dan kenapa harus ada Komunitas Penjaga Budaya Helong? Karena kalau Bendungan Kolhua ini dibangun, akan terjadi genosida terhadap budaya Helong itu sendiri,” ujar Rally melalui sambungan telepon pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Pada 2014, Komnas HAM sebenarnya telah mengeluarkan surat rekomendasi agar pemerintah menghentikan pembangunan Bendungan Kolhua. Surat itu ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM yang sekarang sudah menjadi Menteri HAM Natalius Pigai. Natalius membenarkan bahwa dia menandatangani surat rekomendasi tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, ada empat alasan mengapa pembangunan Bendungan Kolhua harus dihentikan. Pertama, Suku Helong adalah orang asli Kolhua, sehingga mereka tidak seharusnya terusir dari tanah leluhur. Kedua, Suku Helong hidup dari alam sekitar mereka.
Ketiga, di Kolhua terdapat makam leluhur Suku Helong. Keempat, Suku Helong merupakan komunitas yang memiliki kesamaan genealogis dan budaya. “Dari indikator-indikator ini, saya menghubungkan dengan standar dan prinsip HAM yang ada. Sehingga saya menilai bahwa kalau mereka diusir dari satu tempat ke tempat yang lain, maka akan menghilangkan asal-usul nilai budaya dan akar kehidupan mereka,” kata Natalius ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Februari 2025.
Setelah berkali-kali melawan, penolakan Suku Helong membuahkan hasil pada 2022. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, pada saat itu pemerintah telah menganggarkan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dan Review Desain-Model Test-Sertifikasi Desain untuk Bendungan Kolhua. “Namun tidak dapat dilaksanakan karena akses ke lokasi pekerjaan ditutup oleh masyarakat yang melakukan penolakan,” kata dia, Ahad, 2 Februari 2025. Oleh karena itu, kata Diana, Bendungan Kolhua sudah tidak berstatus sebagai PSN dan pembangunanya dibatalkan.
Tempo sudah mencoba menghubungi penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi untuk meminta konfirmasi. Tapi sampai artikel ini diterbitkan, yang bersangkutan belum membalas pesan Tempo.
Pilihan Editor: