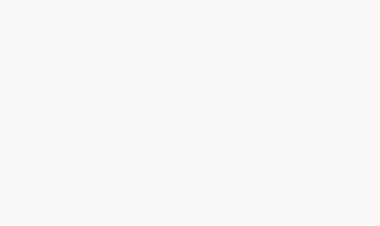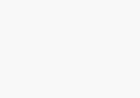Menimbang Ruang di Atas Laut untuk Hunian
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rendra Widyatama, SIP., M.Si., Ph.D (Staf Pengajar senior pada Prodi Ilmu Komunikasi UAD, Alumni S3 Debrecen University Hungary, peneliti media komunikasi dan perilaku khalayak) Baru-baru ini, publik dikejutkan...

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rendra Widyatama, SIP., M.Si., Ph.D (Staf Pengajar senior pada Prodi Ilmu Komunikasi UAD, Alumni S3 Debrecen University Hungary, peneliti media komunikasi dan perilaku khalayak)
Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan pemagaran laut menggunakan bambu sepanjang 30,16 kilometer yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Selain di Tangerang, fenomena serupa juga ditemukan di perairan paten Bekasi dan Surabaya. Di beberapa lokasi, bahkan ditemukan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area tersebut.
Lepas dari pertanyaan siapa yang memasang pagar tersebut dan kontroversi ditabraknya berbagai aturan menyusul dikeluarkannya HGB atas petak-petak laut itu, diskusi terbuka terkait kemungkinan membuka lahan hunian di atas ruang laut perlu dilakukan. Dalam artikel ini saya mencoba memaparkan kemungkinan pemanfaatan ruang laut sebagai hunian, tanpa pretensi politik apapun. Murni untuk kemaslahatan rakyat dan kebaikan negeri.
Tanah Pertanian
Kita sudah paham, luas Indonesia didominasi lautan. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau “United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS) tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km atau 65 persen dari total seluruh wilayah Indonesia. Berarti, daratan hanya 35 persen dari seluruh wilayah Indonesia. Padahal jumlah penduduk Indonesia 282 juta jiwa. Tentu, besarnya jumlah penduduk tersebut membutuhkan lahan hunian yang sangat luas.
Daratan yang hanya seluas 1.919.440 kilometer persegi tersebut tentu tidak bisa dan tidak boleh digunakan untuk perumahan semua. Daratan Indonesia harus ada lahan pertanian untuk memproduksi sumber pangan. Selain itu, harus ada lahan untuk produksi berbagai komoditas penting, misalnya sawit, karet, kopi, teh, dan lain-lain di samping untuk menghasilkan kayu.
Di sisi lain, penduduk Indonesia cenderung bertambah. Data terahir, penduduk kita bertambah 1,11 persen. Berarti, perlu hunian baru yang tidak sedikit. Kebutuhan hunian yang meningkat tersebut akhirnya menyita lahan, termasuk lahan pertanian dan tanah produktif lainnya. Data Kementerian Pertanian menyebut, tidak kurang ada 110 ribu hektar lahan pertanian hilang karena diubah menjadi areal hunian per tahunnya.
Terlebih saat ini pemerintah menargetkan membangun 3 juta hunian baru. Sudah tentu, keadaan ini mengancam upaya ketahanan pangan. Bila ketahanan pangan lemah, Indonesia bisa didikte negara asing yang mengekspor pangan. Oleh karena itu, penggunaan daratan secara ektensif untuk hunian harus dikaji ulang bahkan dihentikan.
Sampai sejauh ini, dalam teknologi pertanian pangan, manusia baru mampu merekayasa tanaman pangan untuk ditumbuhkan di atas tanah daratan. Teknologi penanaman padi, singkong, umbi-umbian, hanya bisa dilakukan di tanah daratan, rawa, hidroponik, maupun aeroponik, namun belum bisa dilakukan di lautan. Pertanian hidroponik dan aeroponik perlu modal sangat besar. Sehingga alternatif menumbuhkan tanaman pangan yang murah hanya di atas tanah daratan. Namun kalau tanah daratan habis digunakan sebagai hunian, bagaimana bisa pemerintah menyediakan pangan untuk rakyatnya?
Laut untuk Hunian
Alih fungsi lahan untuk hunian akan mengancam ketahanan pangan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah membuat hunian di atas ruang laut. Potensi luasan wilayah laut untuk hunian Indonesia sangat luas. Apabila wilayah hunian tersebut dibangun di dekat pantai, maka Indonesia memiliki potensi yang masih sangat luas di mana Indoneisa memiliki 99.083 kilometer pantai. Pemanfaatan 10 persen dari jumlah panjang pantai, rasanya sudah sangat cukup untuk membangun jutaan hunian rumah.
Penggunaan laut untuk hunian tidak mesti harus menimbun lautan menjadi daratan, alias melalui reklamasi. Beberapa alternatif teknologi sudah tersedia untuk keperluan tersebut. Di beberapa wilayah Indonesia, nenek moyang kita sudah memberikan contoh bagaimana rumah didirikan di atas laut. Misalnya pemukiman Suku Bajo di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Pohuwato, Gorontalo, Sulawesi.
Pemukiman nelayan suku Gayo tidak perlu menguruk laut. Rumah-rumah di sana didirikan di atas tiang-tiang kayu yang ditancapkan sebagai penopang. Dengan cara seperti itu, biota laut relatif tetap terjaga. Sudah tentu, kalau negara yang melakukan, tiang-tiang tersebut bisa lebih bagus lagi, sehingga tidak kumuh seperti biasa ditemui di pemukiman nelayan saat ini.
Tentu saja pemukiman di atas laut tersebut harus disertai pengaturan ketat untuk menjaga kelestarian laut. Pemukiman di atas laut harus dilengkapi dengan fasilitas saluran limbah maupun sampah agar tidak langsung dibuang di laut. Bahkan dengan desain yang menarik, hunian di atas laut tersebut dapat diatur sedemikian rupa sehingga memiliki keindahan seperti kota Venesia di Italia, Amsterdam di Belanda, Kerela di India, Bruges di Belgia, Stockholm di Swedia, St. Petersburg di Rusia, atau Suzhou di Tiongkok yang semuanya dikenal dengan kanal-kanal maupun sungai romantisnya. Saya yakin, arsitek-arsitek dan insinyur sipil Indonesia mampu membangun kota di atas laut tersebut dengan indah, selaras dengan alam. Pohon-pohon dan aneka tanaman tetap dapat ditumbuhkan di sana, menggunakan pot-pot raksasa.
Perencanaan Matang
Sudah tentu, hunian di atas laut perlu perencanaan matang, agar tidak ada yang dirugikan. Kajian komprehensif perlu dilakukan, tidak asal membangun dengan mengabaikan kehidupan yang sudah ada pantai, misalnya para nelayan di sana. Nelayan tidak boleh terganggu untuk melaut misalnya jadi lebih boros dalam konsumsi bahan bakarnya, apalagi sampai membuat mereka berhenti menjadi nelayan. Agar penghidupan mereka tetap terjaga, pemukiman nelayan harus ditempatkan di tempat paling depan yang berbatasan dengan laut. Dengan cara seperti itu, mereka tidak akan kesulitan untuk melaut.
Di sisi lain, nelayan juga harus diatur agar kebiasaan buruk yang mereka lakukan selama ini bisa hilang. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lingkungan nelayan umumnya kumuh. Kebersihan dan keindahan hunian seolah tidak menjadi bagian dalam kehidupannya.
Penggunaan wilayah laut untuk pemukiman sudah tentu akan berbenturan dengan berbagai peraturan yang ada. Oleh karena itu, berbagai peraturan tersebut perlu diubah terlebih dahulu. Tidak sulit untuk mengubah peraturan dan undang-undang untuk tujuan yang lebih besar ke depan. Implementasinya perlu perencanaan matang dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan sosial budaya.
Pemanfaatan ruang laut menjadi alternatif solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan lahan daratan dan mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu, penguasaan dan pengaturan hunian di atas ruang laut tersebut harus dilakukan oleh negara, tidak oleh swasta seperti yang disinyalir terjadi saat ini. Bila swasta dilibatkan, maka kolaborasi menjadi kata kunci untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tersebut dilakukan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Saya yakin, Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan tidak akan pusing lagi mencari lahan untuk mewujudkan 3 juta rumah untuk rakyat.