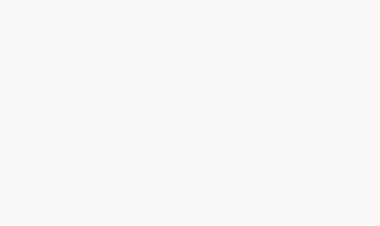Data Penurunan Kemiskinan RI Dikritik: Kenapa Masyarakat Miskin Tetap Banyak?
Pakar ekonomi Wijayanto Samirin menyoroti ketidaksesuaian data statistik ekonomi Indonesia, mencakup aspek kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan biaya logistik, menimbang efeknya pada kebijakan.

Pengamat ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengkritisi ketidakkonsistenan data statistik di Indonesia. Menurutnya, banyak data seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan biaya logistik yang tidak konsisten.
Hal ini disampaikannya dalam acara Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi pada Rabu, (22/1).
“Ketika data menunjukkan tingkat kemiskinan terendah dalam sejarah, tetapi masih banyak masyarakat yang hidupnya susah. Ini karena data tersebut kurang membumi dan seringkali inkonsisten,” ujar Wijayanto.
Garis Kemiskinan yang Tidak Realistis
Terkait data tingkat kemiskinan, Wijayanto menyatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati menggunakan data tersebut sebagai acuan. Ia menjelaskan bahwa garis kemiskinan berdasarkan purchasing power parity (PPP) berkisar antara US$ 2,5 hingga US$ 2,7 per kapita per hari.
Dengan kurs JISDOR pada 22 Januari 2025 sebesar Rp 16.327 per dolar AS, angka ini setara dengan Rp 40.817 hingga Rp 44.822 per kapita per hari. Namun, standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan rendah adalah US$ 3,65 atau Rp 59.593 per kapita per hari.
Sementara untuk negara berpenghasilan menengah ke atas, standar tersebut adalah US$ 6,85 atau Rp 111.839 per kapita per hari. Saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai US$ 4.469 per kapita, sehingga sudah masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas.
"Dengan demikian, acuan garis kemiskinan seharusnya menggunakan standar Bank Dunia yaitu Rp 111.839 per kapita per hari atau sekitar Rp 3,47 juta per bulan,” kata Wijayanto.
Sebagai perbandingan, garis kemiskinan nasional yang digunakan BPS per September 2024 adalah Rp 595.242 per kapita per bulan. Nilai ini terdiri dari Rp 443.433 untuk kebutuhan makanan dan Rp 151.809 untuk kebutuhan non-makanan.
“Ketika mengukur kemiskinan, kita masih menggunakan data yang jauh lebih rendah dari parameter yang disarankan Bank Dunia,” ujarnya.
Tingkat Pengangguran yang Kurang Representatif
Wijayanto juga mengkritisi penghitungan tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan standar nasional, seseorang yang bekerja satu jam per minggu, meskipun tanpa bayaran, sudah dianggap bekerja. Dengan standar ini, tingkat pengangguran hanya mencapai 4,9%.
Acuan tersebut tidak bisa menggambarkan realitas, karena perubahan angka pengangguran sebesar 1% atau 2% menjadi tidak bermakna. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan parameter 35 jam kerja per minggu sebagai acuan bekerja penuh.
"Jika standar ini digunakan, tingkat pengangguran Indonesia sebenarnya mencapai sekitar 30%,” ucapnya.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios)Media Wahyudi Askar menambahkan bahwa ketidakadilan dalam regulasi ketenagakerjaan juga menjadi masalah besar yang berdampak pada tingkat kemiskinan.
“Rezim upah murah masih berlangsung, sehingga banyak masyarakat terjebak dalam utang jangka panjang seperti kredit pemilikan rumah, pinjaman online, dan utang pendidikan anak,” katanya.
Ketimpangan Pendapatan
Menurut Wijayanto, Indonesia saat ini hanya mengukur ketimpangan berdasarkan pengeluaran, bukan pendapatan. Padahal, ketimpangan pendapatan lebih relevan dalam menggambarkan realitas ekonomi.
“Rasio Gini berdasarkan pendapatan akan jauh lebih tinggi daripada berdasarkan pengeluaran. Bahkan, 1% masyarakat menguasai 59% tanah di Indonesia,” katanya.
Rasio Gini mengukur ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, dengan nilai 0 berarti merata sempurna dan 1 berarti ketimpangan maksimal.
Wijayanto juga menyoroti klaim pemerintah terkait penurunan biaya logistik. Dalam pidatonya pada 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa biaya logistik nasional turun dari 24% menjadi di bawah 14% dalam 10 tahun terakhir. Namun, klaim tersebut diragukan.
Penurunan sebesar 10% adalah pencapaian luar biasa jika benar terjadi. Namun, ternyata angka tersebut diperoleh dari pengukuran yang berbeda. Angka 24% mencakup biaya ekspor-impor, sementara angka 14% tidak memasukkan biaya tersebut.
“Inilah contoh inkonsistensi cara pengukuran yang sering muncul dalam data statistik kita. Kita harus berhati-hati menggunakan data ini karena masih banyak hal yang kurang proper,” ujarnya.