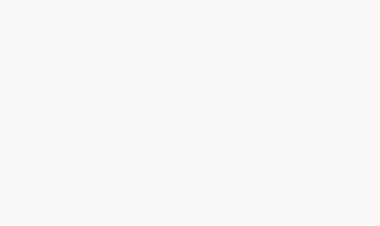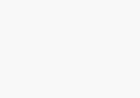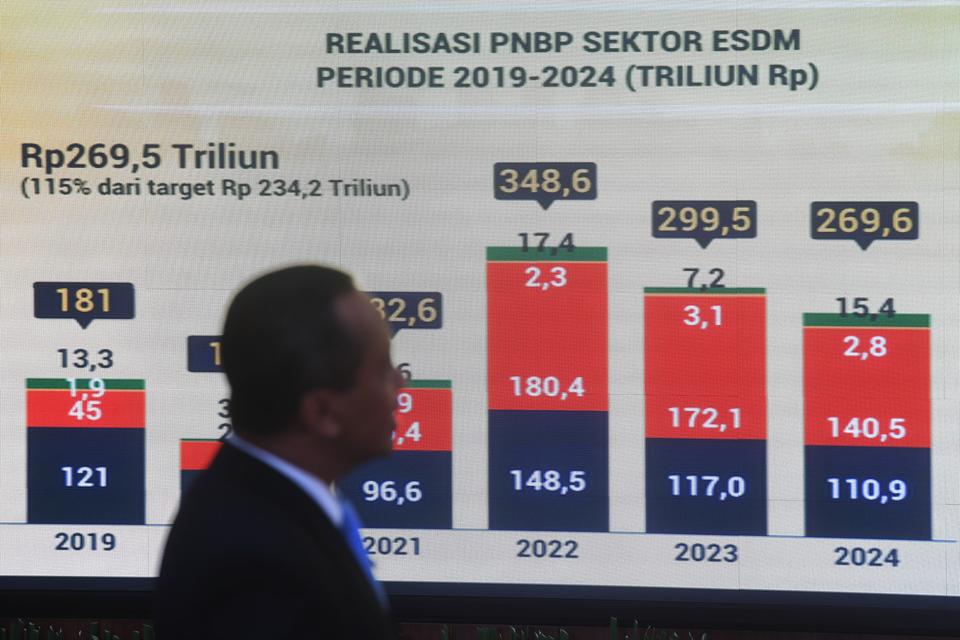Keadilan Lingkungan dan Keberlanjutan Hutan Tropis Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Mohammad Adib (Guru Besar Antropologi Ekologi, Program Doktor Ilmu Sosial, FISIP Universitas Airlangga Surabaya) Alih fungsi hutan lindung seluas 20 juta hektare menjadi food estate (lumbung pangan) berisiko...

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Mohammad Adib (Guru Besar Antropologi Ekologi, Program Doktor Ilmu Sosial, FISIP Universitas Airlangga Surabaya)
Alih fungsi hutan lindung seluas 20 juta hektare menjadi food estate (lumbung pangan) berisiko memicu bom waktu ekologis berupa degradasi lahan, krisis air, dan bencana ekologis. Food estate, yang direncakan segera diberlakukan dengan mengalihfungsikan hutan lindung telah memicu respons keras dari kalangan akademisi, praktisi, dan para pihak peduli lingkungan. Respons keras berupa surat terbuka kepada presiden dan sejumlah tulisan di berbagai media mulai ramai pada pekan pertama bulan Januari tahun 2025 ini.
Para pihak itu mendesak agar kebijakan pro-deforestasi itu diberhentikan segera. Kebijakan tersebut secara kasat mata akan segera melahirkan konflik agraria dan ancaman krisis ekologis. Indonesia merupakan negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo, dengan luas hutan 120 juta hektare.
Indonesia terkenal bukan hanya oleh keanekaragaman hayati dan keanekaragaman ekosistemnya, namun juga merupakan kawasan dengan lahan gambut tropis terbesar kedua di dunia, yang sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim. Konversi 20 juta ha kawasan hutan yang direncanakan ini, akan mengakselerasi angka deforestasi sejumlah 20 juta hektar dalam satu dekade. Angka deforestasi saat itu saja telah melampaui Amazon Brasil pada tahun 2012.
Degradasi Hutan
Alih fungsi hutan menjadi food estate seluas 20 juta hektar akan mengancam kesuburan tanah Indonesia, membuka jalan bagi degradasi lahan yang meluas berupa hilangnya tutupan hutan. Penebangan hutan untuk pembukaan lahan food estate berpeluang menghilangkan lapisan pelindung alami tanah, membuatnya rentan terhadap erosi akibat angin dan hujan. Pengalaman di di Andes, Kolombia deforestasi mendongkrak tingkat erosi hingga 33 persen antara tahun 1972 dan 2010, yang menyebabkan peningkatan signifikan beban sedimen di sungai. Tanah yang terkikis kehilangan lapisan topsoil yang kaya nutrisi, menurunkan kesuburannya secara drastis.
Konversi hutan lindung untuk program food estate sebagaimana diizinkan oleh Permen LHK 24/2020, dalam banyak hal telah menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi fungsi hutan. Deforestasi dan degradasi ini berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Hal ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030.
Pembukaan lahan hutan berskala besar untuk food estate di sejumlah daerah di Sumatra dan Kalimantan juga menyebabkan degradasi lingkungan berupa erosi, pencemaran air, dan kehilangan keanekaragaman hayati, yang pada akhirnya mengancam kesejahteraan masyarakat sekitar. Di Sumatra dan Kalimantan, ekspansi lahan untuk food estate, telah memicu sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat, mengakibatkan hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan Masyarakat.
Konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan seringkali diikuti dengan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan monokultur. Pengalaman di kawasan hutan Pasoh, Malaysia, bahkan konversi kecil 0,2 persen lahan hutan menjadi lahan pertanian, telah secara signifikan meningkatkan hilangnya tanah. Demikian pula di Queensland, Australia, kadar karbon tanah ditemukan jauh lebih rendah di lahan pertanian dibandingkan dengan hutan asli. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lahan, menurunkan kesuburan tanah, dan mengancam produktivitas pangan di masa depan. Dengan kata lain, proyek food estate berpotensi menimbulkan ketidakadilan lingkungan.
Keberlanjutan hutan tropis Indonesia
Menjaga keberlanjutan hutan tropis Indonesia membutuhkan kebijakan yang tegas oleh pemangku kepentingan di tingkat global, nasional, dan lokal baik oleh pemerintah, peneliti-akademisi, dunia usaha, dan warga serta lembaga swadaya masyarakat.
Pertama, United Nation Environment Programme (UNEP), badan dunia yang mengurusi lingkungan (ekologi), sudah seharusnya berperan untuk meningkatkan dukungan dan memfasilitasi kerja sama internasional dalam penerapan antropologi ekonomi (AE) untuk perhutanan sosial (PS) yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia dan negara-negara lain terutama yang memiliki hutan tropis.
Kedua, di tingkat nasional (eksekutif, legislatif - DPR RI-MPR RI), menguatkan regulasi dan alokasi anggaran yang mendukung penelitian, pendidikan, dan penerapan AE dalam PS di Indonesia. Kepada Presiden RI hendaknya memerintahkan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk menetapkan tata ruang dan tata kelola hutan Indonesia. Penetapan tata ruang itu diimplementasikan oleh kementerian terkait.
Ketiga, di tingkat regional pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk menerapkan prinsip-prinsip AE dalam perencanaan dan implementasi program PS di tingkat daerah. Dan keempat, lembaga pendidikan (dasar, menengah, tinggi), mengintegrasikan pengetahuan tentang AE dan dan PS ke dalam kurikulum pendidikan formal. Kemendiktiristek membuka dan menguatkan Program Studi lingkungan/ekologi di jenjang stata 1, 2, dan 3. Menjadi perhatian ekstra bagi perguruan tinggi yang memperoleh mandat untuk mengelola kawasan hutan sebagai bagian dari 1,1 juta ha dari kebijakan Permen LHK (P. 287/2022) tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Jawa. Mengarusutamakan program kampus yang berkelanjutan di Indonesia.
Kelima, Badan Riset Nasional (BRIN), melakukan penelitian mendalam dan komprehensif mengenai penerapan AE dalam PS di berbagai konteks sosio-ekologis di Indonesia. Keenam, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan untuk menguatkan program-program edukasi dan pendampingan masyarakat yang berbasis pada prinsip-prinsip AE untuk mendukung PS yang berkeadilan. Ketujuh, dunia usaha (global, nasional, dan regional) menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan dalam investasi dan kerja sama di sektor kehutanan, dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat.
Publik selayaknya menguatkan kolaborasi untuk mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang kebijakan ini dengan mengutamakan pendekatan berkelanjutan. Menyuarakan kepentingan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan agar mereka tidak menjadi korban dari pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi. Para pegiat lingkungan hendaknya meningkatkan partisipasi aktifnya dalam mengawasi dan mendukung upaya-upaya pelestarian hutan, serta menuntut pemerintah untuk menciptakan tata kelola kehutanan yang adil dan berkelanjutan.