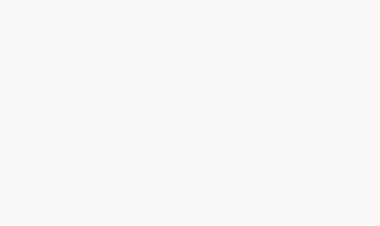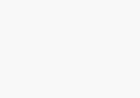Memperkuat Kelembagaan Keuangan Sosial Syariah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keuangan sosial syariah di Indonesia, yang mencakup zakat, infak, sedekah (ZIS), wakaf, dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir....


Oleh : Jaharuddin, Pengamat Ekonomi Syariah, Dosen FEB UMJ
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keuangan sosial di Indonesia, yang mencakup zakat, infak, sedekah (ZIS), wakaf, dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan BAZNAS (2024), total penghimpunan dana ZIS-DSKL hingga kuartal kedua tahun 2024 mencapai Rp 26,137 triliun dengan tingkat pertumbuhan tahunan (YoY) sebesar 68,3 persen. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan sosial syariah, didukung oleh digitalisasi layanan dan meningkatnya jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang kini mencapai 711 lembaga di seluruh Indonesia.
Namun, di tengah pertumbuhan yang menggembirakan ini, distribusi dana zakat masih menghadapi tantangan besar. Sebagian besar dana masih dialokasikan untuk sektor kemanusiaan, keagamaan seperti pembangunan masjid dan program dakwah, sementara pemanfaatan di sektor ekonomi produktif yang dapat mendukung kemandirian masyarakat masih terbatas. Dari perspektif teori kelembagaan, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep isomorfisme koersif (DiMaggio & Powell, 1983), di mana regulasi yang lebih ketat dan insentif pemerintah diperlukan untuk mendorong lembaga zakat agar mengalokasikan dana ke sektor yang lebih berdampak dalam jangka panjang.
Sektor wakaf juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meskipun masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengelolaannya. Berdasarkan data BWI (2024), jumlah tanah wakaf di Indonesia telah mencapai 440.512 titik dengan luas total 57.263 hektar. Sayangnya, sebagian besar pemanfaatan tanah wakaf masih berfokus pada pembangunan tempat ibadah, sementara sektor pendidikan dan ekonomi belum menjadi prioritas utama. Sementara itu, akumulasi wakaf uang telah mencapai Rp2,56 triliun, meningkat 212 persen sejak peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Produk inovatif seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) telah menghimpun dana sebesar Rp1,011,9 miliar, tetapi angka ini masih jauh dari potensi wakaf uang nasional yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun.
Dari sudut pandang teori kelembagaan, sektor wakaf menghadapi tantangan dalam memperoleh legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat. Meyer dan Rowan (1977) menjelaskan bahwa organisasi memperoleh legitimasi dengan menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks wakaf, hal ini berarti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Sayangnya, lemahnya sistem pelaporan dan monitoring sering kali menjadi kendala dalam upaya membangun kepercayaan publik yang lebih luas.
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti Bank Wakaf Mikro (BWM), juga berperan penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil. Hingga tahun 2023, jumlah pembiayaan kumulatif BWM mencapai Rp 122,7 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 67,3 ribu orang. Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan yang baik, total aset LKMS masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Pada tahun April 2024, total aset LKM Syariah hanya mencapai Rp 621,53 miliar, sementara LKM konvensional mencapai Rp958,436 miliar. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing LKMS agar dapat bersaing dengan sistem keuangan konvensional.
Dalam konteks teori kelembagaan, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep isomorfisme mimetik, di mana LKMS perlu meniru praktik-praktik terbaik dari lembaga keuangan konvensional dalam hal inovasi produk dan digitalisasi layanan. Selain itu, diperlukan dukungan regulasi yang lebih fleksibel dan insentif bagi pengembangan LKMS untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Penguatan kelembagaan keuangan sosial syariah di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satu elemen utama yang harus diperkuat adalah regulasi yang adaptif dan progresif. Regulasi saat ini perlu disempurnakan untuk mendukung inovasi produk keuangan sosial syariah, seperti wakaf produktif dan crowdfunding syariah. Pemerintah melalui BAZNAS, BWI, OJK, KNEKS, Perguruan Tinggi dan Masyarakat perlu berkolaborasi dalam merancang regulasi yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini tanpa mengabaikan prinsip syariah.
Selain regulasi, koordinasi antar-lembaga juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Pengelolaan zakat dan wakaf saat ini masih terfragmentasi di berbagai lembaga, yang sering kali menyebabkan tumpang tindih dalam program dan distribusi dana. Scott (1987) dalam konsep organizational field menjelaskan bahwa organisasi yang beroperasi dalam konteks yang sama perlu berbagi sistem regulasi dan norma yang terstandarisasi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, sinergi antara BAZNAS, LAZ, dan BWI harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan dana sosial syariah.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga merupakan faktor krusial dalam memperkuat kelembagaan keuangan sosial syariah. Pengelolaan zakat dan wakaf memerlukan tenaga profesional yang memahami prinsip keuangan syariah dan manajemen keuangan secara modern. DiMaggio dan Powell (1983) dalam konsep isomorfisme normatif menyoroti pentingnya profesionalisasi dalam industri untuk meningkatkan legitimasi dan efisiensi organisasi. Pelatihan dan sertifikasi bagi amil zakat dan nazhir wakaf perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa dana sosial yang dihimpun dapat dikelola secara lebih profesional dan transparan.
Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam penguatan kelembagaan keuangan sosial syariah. Pemanfaatan teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana sosial syariah. Platform digital juga dapat memperluas jangkauan penghimpunan dana, memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dengan lebih mudah, serta memberikan mereka akses terhadap informasi penggunaan dana secara real-time.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah telah meluncurkan Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029 dengan tujuan menjadikan wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Peta jalan ini mencakup langkah-langkah strategis seperti peningkatan literasi wakaf, penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan, pengembangan produk wakaf produktif, serta pemanfaatan infrastruktur digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sektor keuangan sosial syariah di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, penguatan kelembagaan dalam aspek regulasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas SDM sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mengakomodasi, menumbuhkan dan mengembangkan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia yang disemai, dirawat dan ditumbuhkan serta dikembangkan masyarakat dalam bidang keuangan sosial syariah mesti dilakukan pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori kelembagaan, seperti isomorfisme koersif, mimetik, dan normatif, sektor ini dapat berkembang lebih efektif dalam menjawab tantangan yang ada. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, asosiasi, stakeholder lainnya, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menjadikan keuangan sosial syariah sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat.