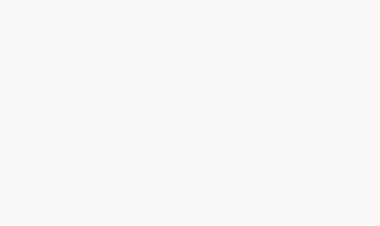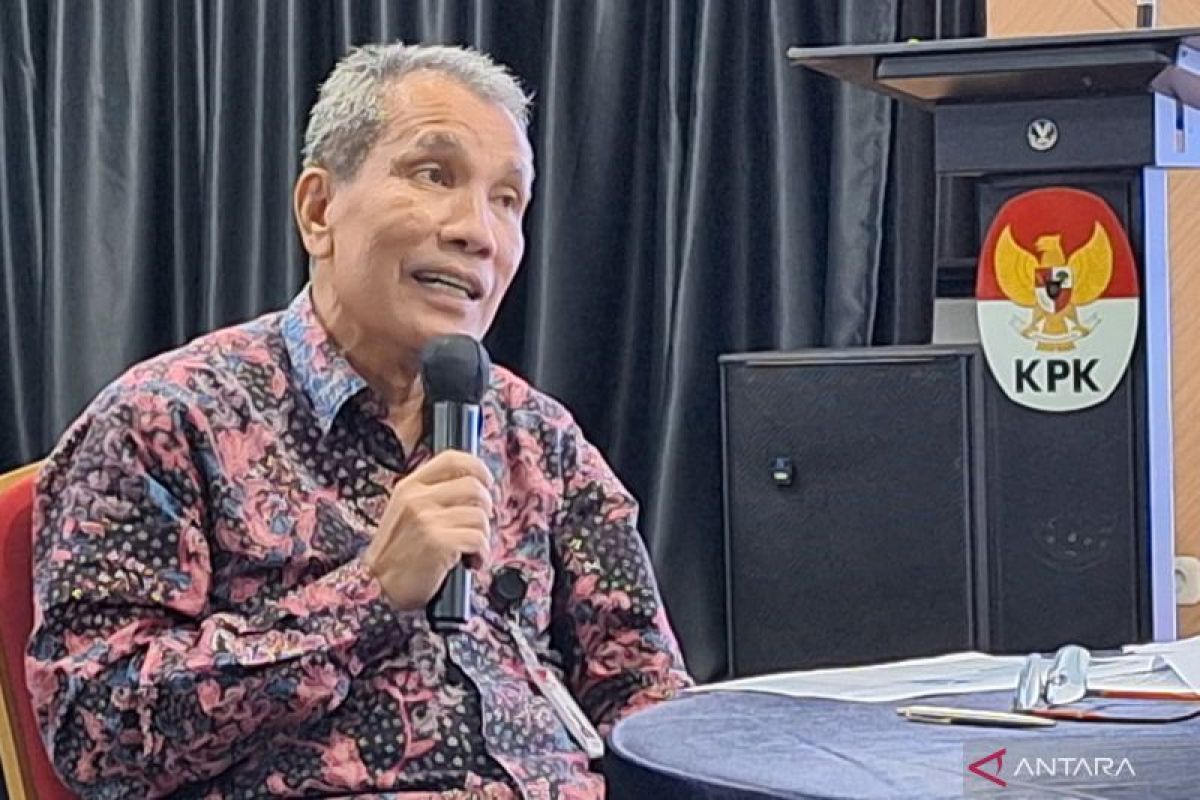Detik-detik Berharga
Sumber foto : Canva Langit pagi itu tampak mendung. Awan hitam bergelayut berat, seolah menahan tangis. Di balkon apartemen lantai 15, aku memandang kota yang masih terselimuti kabut tipis. Gemuruh...
 Syahrial, S.T
Sastra | 2024-11-18
07:34:36
Syahrial, S.T
Sastra | 2024-11-18
07:34:36

Langit pagi itu tampak mendung. Awan hitam bergelayut berat,
seolah menahan tangis. Di balkon apartemen lantai 15, aku
memandang kota yang masih terselimuti kabut tipis. Gemuruh
petir sayup-sayup terdengar dari kejauhan, menggetarkan
jendela-jendela kaca. Angin dingin menyapu wajahku, membawa
aroma hujan yang akan turun.
Aku melirik jam tangan - 07.10. Kegelisahan mulai merayap dalam
dada. Meeting dengan klien besar dari Singapura akan dimulai
pukul 08.00. Presentasi yang kusiapkan semalaman harus
sempurna. Bonus akhir tahun dan promosi jabatan bergantung pada
meeting ini.
"Sepertinya akan hujan, Pak," ujar pak satpam kompleks
apartemen sambil membukakan pintu gerbang. Di matanya terpancar
kekhawatiran tulus. Aku mengangguk, merapatkan jaket, dan
mengenakan masker. Motorku mendengung halus, siap menerobos
jalanan yang mulai padat.
Suara Ibu tadi pagi terngiang di telinga. "Hati-hati di jalan,
Nak. Jangan ngebut. Hidup cuma sekali." Entah sudah berapa ribu
kali dia mengucapkan kalimat yang sama. Dulu, aku sering
mendengus mendengarnya. Terlalu protektif, pikirku. Tapi sejak
kehilangan Ayah dalam kecelakaan tiga tahun lalu, aku mulai
memahami ketakutan dalam suaranya setiap kali aku pamit
berangkat kerja.
Baru lima menit melaju di jalan raya, rintik hujan mulai turun.
Awalnya gerimis kecil, tapi perlahan membesar. Dalam hati, aku
mengutuk ramalan cuaca yang meleset. Harusnya hari ini cerah,
kata aplikasi cuaca di ponselku. Angin bertiup semakin kencang,
menerbangkan daun-daun kering dan sampah plastik. Motorku mulai
oleng, terguncang hembusan angin yang tak bersahabat.
Pikiranku melayang ke kejadian seminggu lalu. Pak Ahmad,
tetangga sebelah apartemen, meninggal mendadak karena serangan
jantung saat berkendara. Masih terbayang jelas wajah pucat
istrinya saat memberitahu berita itu. "Tadi pagi masih sempat
sarapan bersama, masih bercanda seperti biasa," kata Bu Ahmad
di sela isak tangisnya. Kematian memang tak pernah memberi
jadwal kunjungan.
Badai semakin mengamuk. Kilat menyambar-nyambar, diikuti
dentuman guntur yang memekakkan telinga. Pohon-pohon di pinggir
jalan menari liar, beberapa ranting patah dan jatuh ke aspal.
Air hujan yang dingin menusuk menembus jaket dan celanaku. Kaca
helm mulai berembun, mengaburkan pandangan.
Jantungku berdegup kencang. Rasa takut mulai merayap dari ujung
kaki hingga ubun-ubun. Bayangan Ayah yang terbaring kaku di
rumah sakit tiga tahun lalu berkelebat dalam pikiran. Dia juga
terburu-buru di pagi berhujan, seperti aku hari ini. Meeting
penting, katanya waktu itu. Meeting terakhirnya.
"Ya Tuhan, lindungi aku," bisikku dalam hati. Tangan gemetar
memegang setir. Logika mulai berperang dengan ego. Haruskah aku
meneruskan perjalanan? Bagaimana dengan meeting itu?
Reputasiku? Karirku?
Sebuah ranting besar jatuh beberapa meter di depanku. Rem
berdecit keras. Motorku nyaris tergelincir. Napas tersengal,
aku memutuskan untuk menepi ke halte bus terdekat. Ada hal yang
lebih penting dari meeting dan promosi - nyawaku sendiri.
Di halte yang sepi, seorang bapak tua duduk tenang membaca
koran. Rambutnya yang putih tersisir rapi, wajahnya teduh penuh
kebijaksanaan. Dia tersenyum melihatku yang basah kuyup. "Cuaca
memang tidak bisa ditebak, Nak. Seperti hidup ini," ujarnya,
suaranya dalam dan menenangkan.
"Iya, Pak. Tadi saya buru-buru karena ada meeting penting. Tapi
sekarang sadar, lebih baik terlambat daripada celaka," jawabku
sambil memeras ujung jaket yang basah.
"Betul sekali." Bapak itu melipat korannya. "Saya dulu seperti
kamu, selalu mengejar waktu. Sampai suatu hari, jantung saya
kumat di jalan. Terkapar sendirian di pinggir jalan tol.
Beruntung ada yang menolong." Dia menghela napas panjang.
"Sejak itu saya sadar, hidup ini singkat. Setiap detik
berharga. Tak ada meeting atau project yang lebih penting dari
nyawa kita."
Kata-katanya menghantam kesadaranku seperti ombak yang
menerjang karang. Selama ini, hidupku berputar di zona sempit
bernama karir. Meeting, deadline, target, bonus, promosi -
seolah hanya itu yang penting. Aku lupa caranya berhenti
sejenak, menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari,
menelepon Ibu hanya untuk menanyakan kabar, atau sekadar
memandang langit senja dari balkon apartemen.
Setengah jam kemudian, badai mulai mereda. Hujan masih turun,
tapi tidak sederas tadi. Aku pamit pada bapak tua itu,
berterima kasih atas pelajaran hidup yang tak terduga. Dia
tersenyum, menepuk pundakku pelan. "Ingat, Nak. Hidup ini
adalah hadiah. Cara terbaik mensyukurinya adalah dengan
menjalaninya pelan-pelan, menikmati setiap detiknya."
Sisa perjalanan ke kantor kuhabiskan dengan kecepatan normal.
Tak ada lagi pikiran untuk ngebut atau menerobos hujan. Meeting
dengan klien Singapura? Aku sudah mengirim pesan pada tim bahwa
aku akan terlambat karena cuaca buruk. Untuk pertama kalinya
dalam karirku, aku tidak merasa bersalah karena terlambat.
Sesampainya di kantor, wajah-wajah cemas menyambutku. "Astaga,
kamu tidak apa-apa? Tadi badainya parah sekali!" seru Rina,
rekan satu tim.
Aku tersenyum. "Iya, sempat berteduh di halte. Maaf
terlambat."
"Yang penting kamu selamat," ujar Pak Tomo, atasanku. "Meeting
sudah kami undur setengah jam. Ganti baju dulu sana, masih ada
waktu."
Di toilet kantor, aku menatap cermin. Wajah yang memandang
balik tampak lelah tapi ada kilat berbeda di matanya. Pertemuan
singkat dengan bapak tua di halte telah membuka mataku. Hidup
memang seperti badai - bisa datang dan pergi kapan saja, tak
bisa diprediksi, kadang menakutkan. Tapi justru ketidakpastian
itu yang membuatnya berharga.
Kubuka laptop dan mulai menulis pesan untuk ibuku:"Bu, terima
kasih selalu mengingatkan anakmu ini untuk berhati-hati. Hari
ini aku belajar bahwa hidup ini singkat dan berharga. Maaf
jarang menelepon. Nanti malam kita video call ya? Aku kangen
masakan Ibu. Aku sayang Ibu."
Air mata menggenang saat mengetik pesan itu. Berapa kali aku
mengabaikan telepon Ibu karena 'sibuk'? Berapa kali aku menunda
pulang kampung karena 'banyak kerjaan'? Berapa banyak momen
berharga yang kulewatkan karena terlalu fokus mengejar sesuatu
yang fana?
Sejak hari itu, aku mulai menjalani hidup dengan cara berbeda.
Tetap bekerja keras, tapi tidak lupa menikmati prosesnya. Tetap
mengejar mimpi, tapi tidak mengorbankan kesehatan dan
keselamatan. Aku mulai meluangkan waktu untuk hal-hal sederhana
- sarapan tanpa terburu-buru, mengobrol dengan tetangga di
lift, menelepon Ibu setiap hari, atau sekadar memandang
matahari terbit dari balkon.
Karena pada akhirnya, hidup ini adalah anugerah yang tak
ternilai. Setiap detak jantung, setiap tarikan napas, setiap
tawa dan tangis - semua adalah bagian dari perjalanan yang
indah ini. Dan kita tidak pernah tahu, kapan hari ini akan
menjadi hari terakhir kita.
Sekarang, setiap kali mendengar suara hujan, aku tersenyum.
Teringat pelajaran berharga dari sebuah badai dan seorang bapak
tua di halte. Bahwa hidup ini singkat, maka nikmatilah setiap
detiknya seolah-olah hari ini adalah hari terakhirmu di dunia.
Karena mungkin, memang benar demikian.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.