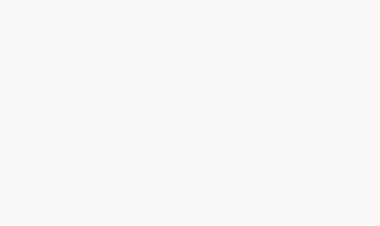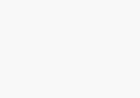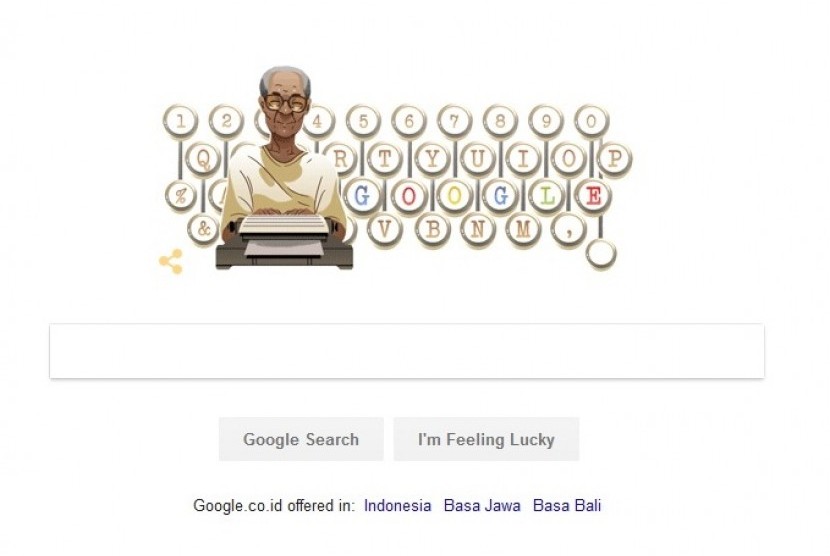Tensi Geopolitik dan Dampak Perubahan Iklim, Swasembada Pangan Jadi Keniscayaan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian meminta semua pihak mendukung target pemerintah menuju swasembada pangan. Ia menilai sudah waktunya, Indonesia mengurangi ketergantungan impor...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian meminta semua pihak mendukung target pemerintah menuju swasembada pangan. Ia menilai sudah waktunya, Indonesia mengurangi terhadap negara lain.
Eliza menjelaskan, saat ini tren global cenderung proteksionis. Setiap negara menjaga keamanan pasokannya, sehingga Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pasar internasional.
Apalagi di tengah tensi geopolitik yang masih terjadi. Semakin banyak ketidakpastian. Hal itu akan memengaruhi perdagangan. "Beberapa negara pun akan cenderung memprioritaskan kebutuhan negaranya, jika negaranya sudah aman barulah akan ada ekspor," kata Eliza, kepada Republika.
Apalagi sekarang, lanjut dia, dampak kian terasa. Keadaan demikian memengaruhi produksi dan distribusi pangan, sehinggga menjadi keniscayaan. Indonesia, jelas Eliza, merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor terbesar di dunia. "Urusan perutnya harus diprioritaskan," ujarnya.
Ia melanjutkan, keberhasilan swasembada ini bergantung pada strategi yang diambil. Jika masih memakai pendekatan lama dan terbukti gagal, maka swasembada pangan sekali lagi akan menjadi jargon dan angan-angan semata.
Eliza menerangkan, menghentikan impor adalah suatu proses bertahap dan membutuhkan strategi yang matang. "Jangan smpai stop impor mendadak ini menjadi backfire bagi pangan kita," ujar pengamat pertanian CORE ini.
Ia mencontohkan kebijakan pembatasan impor jagung tahun 2016, sempat turun 2,17 juta ton, tetapi disaat yg bersamaan terjadi lonjakan impor gandum karena untuk menggantikan jagung pakan. Saat itu Impor gandum naik 3 juta ton.
Oleh karenanya ia mengharapkan upaya serius pemerintah dan berbagai stakeholder terkait. Butuh pendekatan tepat menyentuh akar persoalan. "Intinya apapun niat mulia pemerintah, itu harus disesuaikan dengan kondisi eksisting. Niat baik menyetop impor amat sangat baik dan perlu kita dukung, namun semua berproses agar tidak menimbulkan prsoalan lain," ujar Elza.
"Pastikan dulu strategi yang ditempuh dapat meningkatkan produksi, tidak mengulang kegagalan program-program sebelumnya," tambahnya.
Jika ingin meningkatkan produksi, lanjut Eliza, langkah awalnya adalah beri kepastian harga dan pasar kepada petani. Pastikan yang ditanam petani ini diserap pemerintah lewat badan seperti Perum Bulog misalnya. Dengan adanya transformasi Bulog diharapkan pemerintah tidak hnya fokus pada komoditas beras, melainkan semua komoditas pangan strategis, dan maksimal menyerap hasil panen para petani.
"Ketika ada kepastian pasar dan harga yang berkeadilan, petani kan makluk rasional maka dia akan termotivasi meningkatkan produksinya. Pemerintah jika tidak turun tangan memastikan produk petani diserap, petani akan ragu berekspansi usahanya, dan kuatir jika panen nanti harga jatuh, mereka merugi," tutur Eliza.
Hal ini diiringi dengan kebijakan perbaikan infrastruktur krusial seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan dan jaringan transportasi. Ia kemudian mengungkapkan permasalahan struktural di sektor pertanian dan distribusi pangan. Pertama, Persoalan fundamental yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah banyaknya petani berlahan sempit. Hampir 62 persen petani petani berlahan di bawah 0.5 Ha.
Meski sudah diintensifkan lahannya, sangat sulit mencapai skala keekonomian. Akibatnya biaya per satuan unit menjadi mahal sementara dari sisi harga ditekan tengkulak. "NTP petani pangan selalu lebih rendah dibandingkan NTP perkebunan dan NTP hortikultura, karena margin petani pangan sangat tipis."
Kedua, panjangnya rantai distribusi. Mulai dari tengkulak, penggiling, pedagang grosir, hingga pengecer, yang semuanya menambah margin keuntungan di setiap level. Akibatnya, harga bahan pangan bisa melonjak tajam di tingkat konsumen, tetapi nilai tambah yang diterima oleh petani tetap minim karena mereka berada di bagian paling awal dari rantai pasok, di mana harga pembelian cenderung rendah. Banyaknya middleman (perantara) membuat asimeteris informasi.
"Bargaining posititon petanipun lemah karena bergantung terhadap bandar. Petani menjadi price taker yang mana harganya ini ditentukan bandar," ujar Eliza.
Ketiga, produktivitas rendah dan lahan sempit, sementara biaya produksi semakin tinggi dan harga jual relatif rendah sehingga margin semakin kecil. Misalnya untuk padi, 48 persen biaya produksi padi itu digunakan untuk membayar upah pekerja. Ini karena petani di Indonesia banyak yang terjerat dalam kemiskinan dan kesulitan modal sehingga adopsi teknologi dan inovasinya rendah (termasuk penggunaan benih yg high yielding, climate resilient, pest resilient serta mekanisasi pertanian), diperparah dengan kondisi infrastuktur mendasar seperti irigasi dan jalan usaha tani belum memadai, sehingga produktivitas tanaman terus menurun.
"Mengingat petani kita banyak yang terjerat dalam kemiskinan, kesulitan modal dan kurangnya infrastruktur dasar pendukung menyebabkan rendahnya adopsi teknologi dan inovasi maka pemerintah seharusnya mengubah orientasi belanjanya," kata Eliza
Keempat, pemerintah kurang dapat mengendalikan harga terutama pangan. Hampir 58 persen pengeluaran masyarakat bawah untuk membeli bahan makanan. Ketika harga-harga kurang terkendali, sementara pendapatan petani tidak naik signifikan. "Daya belinya semakin tergerus dan lama-lama akan menggerus kesejahteraan petani," ujar Eliza, menutup pernyataannya.