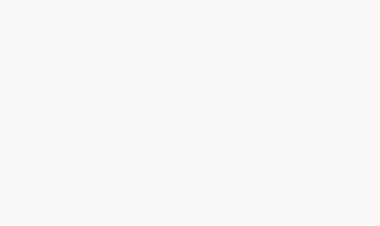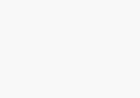Kalut Dikejar Air Laut
Masalah lingkungan jadi risiko global teratas seiring suhu bumi yang terus mencetak rekor. Meningkat kewaspadaan akan bencana alam yang semakin parah, termasuk ancaman air laut.

Masalah lingkungan termasuk cuaca ekstrem menempati peringkat teratas risiko global 10 tahun mendatang, menurut survei terbaru World Economic Forum terhadap 900 ahli, pelaku usaha, pemerintah, dan organisasi sipil. Tahun lalu, cuaca ekstrem melanda berbagai berlahan dunia seiring suhu bumi yang menembus rekor baru. Situasi ini telah meningkatkan kewaspadaan dunia terhadap bencana-bencana alam besar, termasuk ancaman dari laut.
Tahun 2015 sampai 2024 adalah sepuluh tahun terpanas sepanjang sejarah modern. Dan, tahun lalu menjadi pertama kalinya suhu rata-rata menembus target yang disepakati ratusan pemimpin negara, yaitu 1,5 derajat celcius di atas masa pra-industri. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan sepanjang tahun lalu, suhu rata-rata sekitar 1,55 derajat celcius di atas masa pra-industri, melampaui tahun sebelumnya sekitar 1,45 derajat celcius.
Perbedaan suhu sekitar 0,1 derajat ini (sayangnya) bernilai lebih dari hari yang semakin gerah. Para ilmuan telah lama memperingatkan, pemanasan suhu berisiko memicu cuaca ekstrem yang menyebabkan bencana alam yang semakin sering dan parah. Pada Desember, PBB dan Climate Central merilis laporan perdana membahas soal cuaca setahun belakangan dengan judul “When Risk Become Reality: Extreme Weather 2024” yang jika diterjemahkan menjadi “Ketika Risiko Menjadi Kenyataan: Cuaca Ekstrim 2024”.
Dalam laporan itu dipaparkan bagaimana hidup semakin berbahaya lantaran kenaikan suhu (yang disebabkan ulah manusia) menjadi “bahan bakar” bagi cuaca ekstrim. “Cuaca ekstrim telah mencapai tingkatan baru yang berbahaya. Rekor suhu terpanas di 2024 memicu bencana gelombang panas, kekeringan, kebakaran, badai dan banjir yang membunuh ribuan orang dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumahnya,” demikian tertulis dalam laporan itu.
Sekarang, hampir 50 persen kemungkinan suhu akan bertengger di level ini, setidaknya dalam jangka menengah. Dalam laporan yang dirilis tengah tahun lalu, WMO melihat ada 47 persen peluang suhu rata-rata tahunan sekitar 1,5 derajat celcius di atas masa pra-industri menjadi semacam “normal” baru pada periode 2024-2028. Lima tahun sebelumnya, peluang ini terjadi masih nol persen. Risiko “normal” baru ini telah mengerek kewaspadaan dunia terhadap bencana termasuk yang terkait air laut.
Dengan skenario emisi tinggi, Panel Antarpemerintah di bidang Perubahan Iklim (IPCC) di bawah payung PBB memperkirakan rata-rata kenaikan air laut berkisar 0,63 sampai 1,01 meter hingga akhir dekade ini. Namun, kelompok peneliti Nanyang Technological University (NTU) Singapura dan Delft University of Technology Belanda -- dalam studi terbaru berjudul “Fusion of Probabilistic Projections of Sea-Level Rise” atau “Fusi dari Proyeksi-proyeksi Kemungkinan Kenaikan Air Laut” – punya prediksi rentang yang lebih lebar yaitu antara 0,5 sampai 1,9 meter.
“Air laut meluber,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pertemuan dengan negara-negara pulau kecil di Samudera Pasifik, tengah tahun lalu. “Ini situasi yang gila,” ujarnya mengingatkan bagaimana mengkhawatirkannya krisis iklim yang diciptakan oleh manusia ini. “Krisis ini segera berkembang ke skala yang hampir tak terbayangkan, tanpa perahu penyelamat untuk membawa kita kembali ke kondisi aman.” Ia berjanji akan mendorong mobilisasi dana guna membantu negara paling terdampak dan miskin, untuk menghadapi risiko ini.
Beberapa negara pulau kecil sudah meneken perjanjian dengan negara tetangga untuk memungkinkan penduduknya bermigrasi. Menurut perkiraan Global Centre for Climate Mobility yang menangani migrasi dan pengungsian di wilayah rentan problem iklim, beberapa negara tersebut terancam tenggelam di akhir abad ini dan tak lagi berpenduduk pada pertengahan abad ini karena hidup yang semakin sulit dan berbahaya di negaranya.
Namun, bukan hanya negara-negara pulau kecil yang menghadapi situasi semacam itu. Ini bisa jadi masalah massal. Data PBB menunjukkan, hampir separuh penduduk dunia tinggal dalam radius 100 kilometer dari bibir pantai. Mengacu pada berbagai literatur, kota-kota besar berada dekat dengan perairan karena beberapa faktor, di antaranya karena sungai, danau, dan laut adalah rute transportasi penting untuk perdagangan. Laut juga menyimpan banyak potensi ekonomi.
Konsentrasi penduduk di dekat pesisir tergambarkan oleh peta Lumino City 3D buatan Pusat Studi Tata Ruang (CASA) University College London (UCL). Di Indonesia, pesisir Jawa paling padat, sementara di pulau-pulau besar lainnya, konsentrasi penduduk juga tampak di daerah pesisir.
Katadata menghitung sebanyak 36 dari 38 titik pusat ibu kota provinsi berjarak kurang dari 100 kilometer dari bibir pantai. Perhitungan ini dengan menarik garis lurus dari titik pusat ibukota provinsi ke bibir pantai terdekat pada citra satelit Google Earth. Jika dihitung dari titik terluar ibukota, semuanya berjarak kurang dari 100 kilometer dari bibir pantai.
PBB masih menghembuskan harapan, keadaan bisa berbalik membaik. Pemanasan suhu bisa diredam dengan langkah-langkah agresif. Tapi, harapan itu menghadapi tembok-tembok baru. Salah satu negara kontributor polusi terbesar dunia, Amerika Serikat di bawah Donald Trump, akan mundur dari kesepakatn pengendalian iklim Paris Agreement. Sebelumnya, negara-negara eksportir minyak dan gas juga berbalik “menyerang” komitmen bersama soal transisi meninggalkan energi fosil.
Situasi ini meningkatkan dorongan bagi negara-negara untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Ini termasuk relokasi atau migrasi penduduk pesisir dan pulau-pulau kecil hingga megaproyek berdana gila-gilaan.
Penduduk Pasifik Dikejar Air Laut
Pulau-pulau kecil di Samudera Pasifik menghadapi situasi berat. November lalu, Katadata sempat berbincang dengan Perdana Menteri Nuie Hon Dalton Tagelagi di sela-sela Konferensi Iklim PBB COP-29 di Baku, Azerbaijan. Nuie adalah satu dari puluhan negara pulau kecil di Samudera Pasifik. Pemanasan suhu, kata dia, bukan hanya membuat kenaikan air laut, tapi rusaknya karang -- ekosistem penting untuk sektor perikanan sekaligus tembok pemecah ombak alami. Maka itu, pemimpin negara jadi emosional ketika bicara soal komitmen menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat di atas masa pra-industri. “Jika tidak, kami hilang,” ujar Tagelagi.
Apa yang dibicarakan Tagelagi mengingatkan Katadata pada obrolan dengan Arkeolog Palau Island McMichael Mutak di sela-sela konferensi yang sama. “Jadi, negara Anda terancam tenggelam?” tanya Katadata, membuka obrolan. Mutak lalu memperlihatkan di layar telepon selularnya citra satelit negaranya. Garis biru terang mengelilingi pulau yang mirip dinosaurus di antara Maluku dan Filipina tersebut. “Dilindungi karang?” kata saya, yang dijawabnya dengan senyum. Bentangan karang itu “benteng alami” terdepan Palau Island, selama berabad-abad. Maka itu, Palau terus mengangkat masalah kerusakan karang dalam berbagai forum global. “Di bagian lain, ada mangrove yang menjaga, di bagian yang tidak ada, ada juga tembok laut yang dibangun,” ujarnya.
Pemerintah Palau dengan bantuan dana dari sahabat dekatnya, Amerika Serikat dan Jepang, juga melakukan konservasi pulau. Mutak mengirimkan tautan . Ini komik tentang bagaimana pemerintah Palau dengan bantuan Jepang mengombinasikan cara-cara nenek moyang dan modern untuk menjaga pulau dan peninggalan sejarah, agar tidak hilang atau hancur karena banjir yang semakin sering dan jauh merangsek ke daratan.
Dalam rentang ratus tahun, saat suhu masih di bawah level saat ini, Samudera Pasifik telah kehilangan pulau-pulau kecil. Pada 2019, sejumlah ilmuan Australia melaporkan tenggelamnya lima pulau karang kecil dalam teritori Solomon Island, gugusan pulau yang pernah diduga sebagai lokasi tambang emas Raja Salomo alias King Solomon. Satu pulau di antaranya terdeteksi hilang di 2011. Di luar itu, enam pulau dilaporkan mengalami abrasi atau pengikisan tanah yang parah. Solomon Island yang terletak sekitar 2,000 kilometer dari batas darat paling timur Indonesia, dilaporkan mengalami kenaikan air laut tiga kali lipat dari rata-rata global.
Namun, keadaan paling darurat dihadapi tetangga Solomon Island seperti Maladewa, Kiribati, Tuvalu, dan Marshal Islands. Daratan di keempat negara itu hanya sekitar 1 meter dari permukaan laut. Organisasi yang menangani migrasi dan pelarian manusia terkait iklim, Global Centre for Climate Mobility memperkirakan negara-negara pulau tersebut tak lagi berpenghuni pada pertengahan abad ini karena migrasi penduduk, kemudian tenggelam di akhir abad ini.
Migrasi jadi pilihan, meski penduduk dan pemerintah negara terus menyampaikan keinginan untuk bertahan dan “menuntut” bantuan dana dari dunia untuk misi penyelamatan.
Tuvalu telah menandatangani perjanjian kerja sama yang antara lain memuat tawaran bagi 280 warga negara Tuvalu tiap tahunnya untuk menjadi penduduk tetap atau permanent resident di Australia. Angka ini sekitar 2,5 persen penduduk Tuvalu. Dengan perhitungan kasar, jika 280 orang warga per tahun mengambil tawaran ini dan bermigrasi ke Australia, maka negara itu bisa berujung tak berpenduduk dalam kurun waktu 40 tahun.
Beberapa penduduk negara pulau lainnya bisa bermigrasi tanpa perjanjian khusus. Penduduk Marshal Island, Micronesia, dan Palau Island, bisa tinggal, bekerja, atau belajar di Amerika Serikat tanpa visa. Ini karena adanya hubungan diplomatik spesial dengan Amerika Serikat. Tawaran ini semacam “barter” dari pemberian “izin” kepada militer Amerika Serikat untuk berada di negara tersebut, bahkan menempatkan pangkalan militernya.
Kerja sama dengan Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia jadi pilihan bagi penduduk negara-negara pulau kecil yang terdesak oleh kekacauan iklim di Samudera Pasifik. Tapi, yang memiliki dataran tinggi masih berusaha untuk bertahan. Pemerintah Nauru dan Fiji Island misalnya, mulai menjalankan rencana relokasi penduduk ke dataran yang lebih tinggi dan menuntut urunan dana tanggung jawab iklim dari negara-negara kaya kontributor polusi.
Problemnya, pendanaan internasional berat, apalagi dengan Amerika Serikat mundur dari komitmen pengendalian iklim. Dalam satu sesi diskusi di sela-sela konferensi iklim COP29, November lalu, Menteri Energi Terbarukan Nauru menjadi emosional ketika bicara megaproyek relokasi yang diberi nama High Ground Initiative alias Inisiatif Dataran Tinggi. “Saya pikir, datang ke COP tahun ini membuat saya bertanya-tanya. Berapa banyak COP yang harus daya datangi agar didengar. Kami telah melakukan studi, kami membutuhkan pendanaan,” ucapnya, kesal.
Peta Daratan yang Berada di Bawah Level Banjir Tahunan
pada 2100
Indonesia SOS Air Laut
Banyak pulau kecil di Indonesia dibayangi risiko yang sama. Data pemerintah menunjukkan, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau terdaftar, hampir 15 ribu merupakan pulau kecil dengan luas kurang dari 2,000 kilometer persegi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pernah memperingatkan sebanyak 115 pulau kecil terancam tenggelam pada akhir abad ini, dengan 92 di antaranya disebabkan oleh naiknya permukaan air laut. Selain air laut yang naik, penurunan muka tanah jadi faktor lain yang mempercepat tenggelamnya pesisir atau pulau.
Pada 2021 lalu, Climate Central meluncurkan peta yang memberikan gambaran daratan yang dalam berisiko terendam air laut dalam ratusan tahun ke depan imbas kenaikan suhu bumi. Di Indonesia, dengan skenario 1,5 derajat celcius (warna biru pada peta) dan 2 derajat celcius (warna merah pada peta), wilayah paling terdampak berada pada pesisir dalam Pulau Sumatera, dari Aceh hingga Lampung. Pesisir Kalimantan termasuk Ibu Kota Negara Nusantara, Banjarmasin, dan Pontianak. Lalu, sepanjang pesisir dalam Papua. Dan, sepanjang pesisir pantai utara Jawa, dari Jakarta hingga Surabaya, dan pesisir selatan di Cilacap.
Dengan skenario moderat, beberapa lokasi di wilayah-wilayah pesisir tersebut berada di bawah level banjir tahunan pada 2030. Ini menjelaskan banjir yang semakin sering atau parah melanda wilayah-wilayah tersebut.
Prediksi-prediksi Climate Central tentang daratan yang berisiko tenggelam bisa terjadi lebih cepat, bila mengingat Indonesia terus bergelut dengan masalah turunnya permukaan tanah seperti disinggung BRIN. Penyedotan besar-besaran air tanah membuat permukaan tanah di Jawa dilaporkan turun 20-30 sentimeter per tahun, jauh di atas kenaikan permukaan air laut di Indonesia yang berkisar 0,8 sampai 1,2 sentimeter per tahun menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Ditambah lagi, Indonesia juga menghadapi masalah hilangnya benteng-benteng alami penahan air laut. Berdasarkan data pemerintah dan laporan organisasi nonprofit, hutan mangrove beralih fungsi menjadi tambak udang, lahan pertanian, hingga infrastruktur.
Peta Daratan yang Berada di Bawah Level Banjir Tahunan
pada 2030
Peta Perbandingan Dampak Pemanasan Global 1,5 ºCelcius dan 2 ºCelcius pada Ratusan Tahun ke Depan
Adaptasi Air Laut: Antara Melawan Atau Berdamai dengan Alam
Megaproyek tembok atau daratan penahan air laut diadopsi banyak negara dari mulai Belanda, Korea Selatan, Inggris, Italia, Jepang, hingga Indonesia. Namun, ada juga yang memilih atau mengombinasikan solusi yang kerap disebut “menantang” alam ini dengan solusi yang “berdamai” dengan alam: larangan atau relokasi perumahan di pesisir, penanaman bakau besar-besaran, hingga eksperimen kota terapung alias floating city.
Baru-baru ini, Selandia Baru dilaporkan mengeluarkan kebijakan yang melarang pembangunan perumahan di lokasi rentan bencana, termasuk dekat pantai. Larangan semacam ini juga diterapkan Jepang. Sedangkan Maladewa yang 80 persen datarannya hanya sekitar 1 meter di atas permukaan laut bakal memiliki kota terapung atau floating city pertama di dunia. Sementara itu, proyek rehabilitasi mangrove bergulir di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
Indonesia dalam situasi SOS dengan banjir tahunan di pesisir Jawa yang menjadi lokasi sentra-sentra industri dan konsentrasi penduduk. Sejauh ini, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan ide perluasan proyek tembok atau daratan penahan air laut untuk mengatasi problem itu. Pemerintah menyatakan menggaet Korea Selatan dan Belanda yang berpengalaman di megaproyek semacam ini. Sementara ini, estimasi biaya jika megaproyek dilakukan mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, kepastian megaproyek menunggu hasil studi.
Ahli Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan perlunya studi untuk mendapatkan solusi terbaik. “Yang diobati penyebabnya,” ujar Nirwono. Kalau banjir rob – banjir air laut -- karena penurunan muka tanah, maka jawabannya larangan penyedotan air tanah. Untuk merespons masalah air laut naik, solusinya bisa menggeser pemukiman dari pesisir, lalu membuat hutan mangrove atau hutan pantai untuk benteng alami yang tidak mengganggu aktivitas nelayan.
Menurut pendapat dia, solusi melawan laut dengan pembangunan tembok laut bisa berkonsekuensi pada beban keuangan yang menggunung karena biaya perawatan, penguatan, hingga peninggian. “Kalau disebut ini rencana terbaik, harus ada rencana-rencana pembandingnya,” ujarnya.
Ramalan Lonjakan Pengungsi, Korban Jiwa, dan Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim
Berdasarkan laporan lembaga penyedia data dan analisis seputar pengungsian lokal IDMC, jumlah orang yang terpaksa pindah dari tempat tinggalnya karena konflik maupun bencana alam terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, jumlahnya mencapai 46,9 juta orang, separuhnya karena bencana alam. Ini data pengungsian dalam negara, belum yang lintas negara.
Regional Asia Timur dan Pasifik dimana Indonesia menjadi “penyumbang” terbesar kedua di dunia setelah sub-Saharan Afrika. Jumlah pengungsi di regional ini mencapai 10,5 juta orang, dimana hampir 90 persennya atau sembilan juta orang mengungsi karena bencana, terbanyak akibat badai, topan, dan banjir – bencana-bencana yang kembali mendominasi di 2024 hingga awal 2025 ini.
Gelombang pengungsi iklim berpotensi semakin besar seiring rapor merah negara-negara dalam mengendalikan iklim. Lembaga nirlaba yang mengurus migrasi manusia, Organisasi Internasional di Bidang Migrasi (IOM) memprediksi jumlah manusia yang bermigrasi karena bencana alam terkait perubahan iklim bisa mencapai 216 juta pada 2030 – mendekati angka total penduduk Indonesia.
Organisasi nirlaba di bidang kerja sama pemerintah dan swasta, World Economic Forum (WEF), memprediksi perubahan iklim akan menyebabkan tambahan 14,5 juta kematian dan US$ 12,5 triliun atau lebih dari Rp 200.000 triliun kerugian ekonomi di seluruh dunia pada 2050. Ini sejalan dengan hasil survei WEF bahwa masalah lingkungan merupakan risiko global teratas.