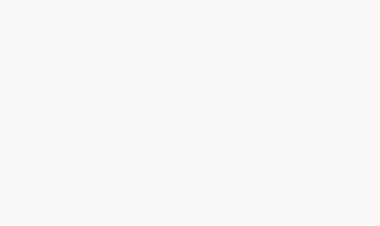Pagar Laut, ‘Bluewashing’, dan Keadilan Akses Maritim
Dalam kasus pagar laut, pemerintah seharusnya tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Kontroversi pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang mengundang kegelisahan publik. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi merusak ekosistem pesisir dan menghalangi hak nelayan kecil untuk mengakses laut.
Merujuk pada Pasal 75 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemanfaatan pesisir dan pulau kecil tanpa izin lokasi dapat dipidana tiga tahun dan denda Rp500 juta. Sedangkan jika tidak memiliki izin pengelolaan, sesuai dengan Pasal 75A, diancam penjara 4 tahun dan denda Rp2 miliar.
Aturan pemberian izin sudah sangat jelas. Artinya, terlepas siapa pun yang menginisiasi pembangunan pagar laut tersebut, jika dilakukan tanpa izin, seharusnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Secara umum, aktivitas tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip common property resources (CPRs), yang mengacu pada hak masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sifatnya milik bersama. Pemasangan pagar laut secara sepihak melanggar hak akses masyarakat lokal, terutama nelayan tradisional yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.
Kini, berbagai argumentasi pemasangan pagar laut pun muncul sebagai dalih keberlanjutan atau perlindungan ekosistem laut. Misalnya, klaim bahwa pagar tersebut digunakan untuk melindungi kawasan laut dari abrasi atau pencemaran laut. Apabila argumentasi tidak didukung dengan transparansi, data ilmiah, dan keterlibatan komunitas lokal, serta dibungkus narasi blue economy tanpa dasar yang jelas, maka alasan tersebut hanyalah bentuk bluewashing.
Bluewashing merujuk pada praktik di mana perusahaan, pemerintah, atau pihak lain menggunakan narasi keberlanjutan atau perlindungan lingkungan sebagai kedok untuk menutupi atau membenarkan kegiatan yang sebenarnya merusak ekosistem laut atau lingkungan secara lebih luas.
Pagar laut yang diklaim untuk mencegah abrasi, berpotensi dijadikan alasan untuk memfasilitasi cikal bakal proyek pembangunan eksklusif seperti reklamasi pantai sebagai bentuk manipulasi yang bertujuan mengamankan kepentingan komersial dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan. Perlu digarisbawahi, pemasangan pagar laut secara diam-diam tanpa alasan yang jelas, atau dengan dalih keberlanjutan (bluewashing), tidak hanya memperburuk kerusakan lingkungan tetapi juga memperlebar ecological debt dalam lingkup domestik.
Ecological debt pada dasarnya merupakan utang ekologis akibat eksploitasi berlebihan oleh pemilik modal besar. Ini memicu ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika sumber daya alam telah mencapai titik kritis atau rusak parah, seperti terumbu karang yang hancur, padang lamun yang lenyap, atau pencemaran berat di perairan, beban pemulihan justru dilemparkan kembali kepada masyarakat umum dan menggunakan anggaran publik.
Maka dari itu, pendekatan gerakan lingkungan yang tumbuh dari inisiatif komunitas lokal (environmentalism from below) bisa menjadi solusi untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk laut, tidak hanya inklusif tetapi juga melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Dauvergne, 2023).
Pendekatan ini fokus pada perjuangan hak atas sumber daya alam, keadilan ekologis, dan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat, berbeda dari pendekatan top-down yang didominasi oleh kebijakan pemerintah atau korporasi. Ini sering melibatkan advokasi akar rumput, aksi kolektif, dan pemberdayaan komunitas untuk melawan eksploitasi dan ketidakadilan lingkungan. Untuk itu, diperlukan beberapa mekanisme kebijakan terkait, sebagai berikut:
Pertama, pembentukan kawasan konservasi perairan (Marine Protected Areas/MPAs) berbasis komunitas yang dirancang dan dikelola oleh masyarakat lokal, dengan dukungan pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) (Bassey, 2024). Komunitas ini melibatkan masyarakat lokal, nelayan, dan ilmuwan untuk memetakan area pesisir yang mengalami degradasi atau sering menjadi lokasi aktivitas ilegal seperti pagar laut.
Selain itu, komunitas perlu diperkuat dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah dan forum dialog terbuka untuk menyepakati tata kelola kawasan perlindungan, aturan, dan zona larangan kegiatan tertentu. Pengawasan komunitas yang aktif dan adanya mekanisme pelaporan terbuka memastikan bahwa setiap tindakan ilegal, seperti pemasangan pagar laut tanpa izin atau aktivitas yang merusak ekosistem, akan segera diketahui dan dapat ditindaklanjuti.
Kedua, penegakan hukum dengan dukungan teknologi dan komunitas. Teknologi modern dan pengawasan berbasis komunitas dapat memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal. Teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS) yang direncanakan untuk diterapkan di seluruh kapal perikanan pada tahun 2025 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pengawasan aktivitas ilegal di sektor kelautan.
VMS dapat diintegrasikan dengan satelit atau drone (vessel viewer) untuk memberikan visual langsung dari aktivitas di lokasi. Selain itu, VMS bisa dintegrasikan dengan AIS (Automatic Identification System) untuk pelacakan pergerakan kapal kecil. Aktivitas dilaporkan melalui AIS, kemudian dikonfirmasi dengan data VMS.
Dengan analisis data historis, VMS dapat mendeteksi pola berulang dari kapal tertentu, seperti aktivitas kapal yang sering berhenti di lokasi tertentu, pola zigzag, jalur berulang untuk pemasangan struktur tertentu, atau menunjukkan pola pengangkutan material. Proses ini menciptakan audit trail digital yang memungkinkan pihak berwenang memverifikasi aktivitas kapal dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system). Namun, penting untuk memastikan implementasinya dilakukan dengan adil, sehingga tidak menciptakan ketimpangan baru atau merugikan nelayan kecil.
Data VMS dikelola secara terbuka dan dapat diakses oleh komunitas nelayan dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa negara bahkan merilis VMS mereka secara publik di peta Global Fishing Watch (globalfishingwatch.org). Ini memastikan bahwa pengawasan tidak hanya diarahkan pada kelompok tertentu, tetapi mencakup semua aktivitas pergerakan kapal, termasuk aktivitas kapal milik perusahaan besar.
Ketiga, proporsionalitas pengawasan di mana setiap kebijakan kelautan harus memperhatikan skala usaha nelayan. Nelayan kecil atau artisanal yang beroperasi di zona perairan terbatas sebaiknya tidak dikenakan aturan yang sama ketatnya dengan kapal besar yang melakukan operasi skala industri yang lebih besar.
Hal ini untuk menghindari sisi negatif efek panopticon, sehingga implementasi kebijakan harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak mengarah pada pengawasan yang represif. Kebijakan harus memprioritaskan pencegahan aktivitas ilegal tanpa menciptakan rasa ketakutan atau tekanan berlebih pada nelayan kecil.
Secara keseluruhan, pemerintah perlu menerapkan pendekatan berbasis keadilan biologis (biojustice) melalui penguatan pengawasan hukum, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, dan penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Regulasi yang lebih ketat harus diberlakukan untuk melarang setiap aktivitas ilegal dan memastikan akses adil ke wilayah perikanan tangkap bagi seluruh nelayan kita.